Aku duduk di bangku kayu di tepi sungai berwarna pink keruh, dengan arusnya yang aneh, mengalir dari rendah ke tinggi. Airnya tampak tak wajar, dan riak-riaknya berbunyi seperti suara parau pria tua penjual buah di pasar, marah-marah tanpa alasan. Aku merasa tempat ini tak nyata, tapi tetap tinggal, seolah menunggu sesuatu.
Orang-orang bermain air di kejauhan. Tidak ada yang berani berenang, hanya melempar batu kecil ke sungai. Ketika batu-batu itu menyentuh permukaan, seekor makhluk serupa naga muncul, mengeluarkan suara mengerikan sebelum kembali menyelam. Sementara aku sendirian di sebuah bangku panjang. Tak seorang pun mau mendekat, mungkin kehadiranku membawa aura yang tidak menyenangkan.
Di seberang sungai, seorang lelaki berdiri. Tidak bergerak, hanya memperhatikanku. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Aku membalas tatapannya. Kita seperti sedang adu kekuatan. Siapa yang bisa bertahan lebih lama tanpa berkedip. Tapi angin yang tiba-tiba menyibak rambutku membuat mataku terpaksa terpejam. Ketika kubuka kembali, dia tersenyum tipis.
Aku lantas beranjak menuju pemandian air panas di puncak bukit. Namun itu bukan kolam biasa. Kubangannya tampak seperti wajan raksasa yang dialasi lava di bawahnya. Orang-orang tampak menikmati suasana di tempat itu. Tubuh mereka telanjang, termasuk aku. Mereka berendam, membiarkan gelembung-gelembung hangat yang meletup dari dasar kubangan membelai kulit.
Awalnya tubuhku terasa nyaman, tetapi perlahan efek di kakiku berlaku sebaliknya, mulai dingin lalu kaku. Dingin itu menjalar ke atas, hingga aku mulai panik dan berteriak. Seorang petugas dengan sendok kayu raksasa mengangkatku, tapi aku terlempar jatuh, tepat di atas jaring yang memisahkan dua ruangan aneh.
Di depan jaring itu, ada dua pintu besar. Aku memilih satu pintu dan melangkah masuk. Seekor gorila menyambutku. Tubuhnya besar dan matanya tajam. Ia mendekat dan menarikku dengan kekuatannya. Awalnya aku melawan, tapi cengkeramannya kokoh. Ketika ia mendekatkan wajahnya, aku merasa aneh. Ada sesuatu yang membuatku berhenti berontak. Aku justru menikmatinya, sebuah perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya, campuran antara takut, pasrah, dan gairah.
Namun segalanya berubah ketika aku membuka mata. Aku tidak lagi bersama gorila. Aku berada di atas rak buku, di atas kertas-kertas lusuh sebuah buku terbuka. Lelaki yang tadi melihatku ada bersamaku, memelukku dengan erat. Kami lantas bercinta, tubuh kami menyatu dengan panas dan desakan. Suaranya memanggil-manggil namaku. Aku tidak mengerti bagaimana dia tahu namaku tapi aku tidak terlalu menghiraukan.
Tiba-tiba, sesuatu jatuh dari atas. Sebuah benda berat menghantam tubuh kami. Aku merasa terhimpit. Ternyata sebuah buku besar bersampul putih. Sampulnya bergambar bukit, api, air, dan sebuah jembatan yang terbentuk dari susunan kata-kata. Lelaki itu memelukku dari belakang, telanjang dan penuh keringat. “Buku ini menutup kisah kita,” bisikmu, “tapi kita bisa melanjutkannya di buku yang lain.”
Aku tidak sempat bertanya apa maksudnya. Dia mendorongku ke belakang, ke sebuah ruang gelap yang terasa seperti dasar dunia. Ketika akhirnya aku membuka mata, aku masih bisa melihat wajahnya. Bahkan tampak lebih jelas dari sebelumnya. Dia tersenyum, sebuah senyum yang aneh, menarik ke atas seperti ketika pertama kali kami bertemu di seberang sungai pink itu.
“Apa ini nyata?” tanyaku dengan suara bergetar.
“Nyata itu relatif,” jawabmu, suaramu bergema di ruang gelap itu. “Semua ini adalah bagian dari cerita.”
“Kisah siapa?”
“Kisah kita.”
Aku merasakan sesuatu dalam genggamanku. Buku bersampul putih itu ada di tanganku, dengan tulisan di halaman pertama yang berbunyi: Sungai Pink, Puncak Bukit, dan Ruang Gelap. Aku membuka halaman berikutnya, ada tulisan lain: Cerita ini tidak pernah berakhir, karena setiap akhir hanyalah awal dari kisah baru. Aku menutup buku itu, memeluknya erat, dan tersenyum samar. Untuk pertama kalinya aku merasa damai.
Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhku. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai kamar. Napasku terengah-engah. Spontan aku teringat buku, lalu menyadari mimpi itu—jika bisa disebut mimpi—terasa nyata, hingga aku ragu apakah yang kualami hanyalah ilusi atau sesuatu yang lebih dari itu.
Aku mencoba menepis pikiran itu. Setelah mandi, sarapan seadanya, dan menghabiskan secangkir kopi, aku mengenakan pakaian formal dan bersiap menuju kampus. Pekerjaanku sebagai dosen di universitas membutuhkan perhatian penuh, bukan pikiran-pikiran menggelikan tentang sungai pink atau buku bersampul putih.
Namun, rasa aneh itu tidak hilang. Sesuatu seperti bisikan samar menggema di sudut pikiranku, memanggilku kembali ke perasaan ganjil yang kurasakan dalam kisah itu. Sesampainya di kampus, aku berjalan melalui lorong panjang menuju ruang dosen. Para mahasiswa berlalu-lalang, beberapa melambaikan tangan padaku, tapi aku hanya mengangguk kecil tanpa benar-benar melihat mereka.
Lalu, aku melihatnya. Seorang lelaki berdiri di ujung lorong. Tubuhnya tinggi, posturnya tegas, dan wajahnya, aku mengenalnya. Itu dia, lelaki dari seberang sungai pink.
Aku terpaku. Dadaku sesak. Dalam sekejap pikiranku dipenuhi bayangan senyumnya, tatapan dinginnya, dan suaranya yang bergema. Ketika ia berbalik dan berjalan menuju perpustakaan, tanpa berpikir panjang, aku mengikutinya.
Perpustakaan sepi pagi itu, hanya ada beberapa mahasiswa yang sibuk dengan laptop dan catatan mereka. Aku memperhatikan lelaki itu dari kejauhan. Dia berjalan perlahan di antara rak-rak buku, jarinya menyusuri punggung buku-buku dengan hati-hati, seakan mencari sesuatu yang sangat spesifik.
Aku mencoba terlihat biasa saja, berpura-pura mencari buku. Namun, mataku terus mengawasinya. Lalu dia berhenti. Tangannya meraih sebuah buku dari rak. Hatiku mencelos. Buku itu memiliki sampul putih, dengan gambar bukit, api, air, dan sebuah jembatan yang terbentuk dari susunan kata-kata. Buku yang sama seperti dalam kisah itu. Aku mendekat perlahan, mencoba melihat lebih jelas tanpa menarik perhatiannya.
“Apakah kau mencariku?” Suaranya tiba-tiba terdengar.
Aku terkejut. Dia menoleh, dan senyumnya yang khas kembali terlihat di wajahnya. Senyum yang aneh, sedikit menarik ke atas.
“Aku?” Aku tergagap, tidak tahu harus berkata apa.
Dia mengangkat buku bersampul putih itu, memperlihatkannya padaku. “Kau mengingat ini, bukan?” tanyanya dengan suara tenang, tetapi nadanya penuh misteri.
“Kita pernah bertemu sebelumnya?” tanyaku, mencoba menguasai diriku.
Dia tertawa kecil. “Pernah? Pertanyaan itu tidak relevan. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita pernah berpisah?”
Aku merasa tubuhku merinding. Perasaan aneh kembali menghantamku.
“Ini hanya mimpi,” gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri daripada kepadanya. “Sungai pink di puncak bukit, buku itu, semua hanya ilusi.”
Dia menggeleng pelan, lalu membuka buku itu. Halaman pertama menunjukkan tulisan yang sama dalam kisah itu: Sungai Pink, Puncak Bukit, dan Ruang Gelap. Dia membalik halaman demi halaman, dan setiap kata yang tertulis di sana adalah bagian dari apa yang kualami.
“Apa maksudnya?” tanyaku, suaraku bergetar.
Dia menatapku tajam, tatapan yang membuatku merasa telanjang, terpapar sepenuhnya. “Sungai pink itu bukan ilusi, dan buku ini adalah kunci. Kau sudah tahu itu. Aku hanya menunggu kau menyadarinya.”
“Tapi kenapa aku? Apa yang sebenarnya terjadi?”
Dia menutup buku itu dengan suara pelan. “Karena kita adalah cerita itu, dan cerita ini belum selesai.”
Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia berjalan menjauh, meninggalkan buku itu di meja. Aku berdiri mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dorongan aneh membuatku meraih buku itu. Ketika aku membuka halaman baru, aku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya, sebuah gambar diriku sendiri, duduk di tepi sungai pink, menatap lelaki dari seberang.
Aku melihat lebih dekat, dan seketika gambar itu bergerak. Sungai pink itu hidup, makhluk naga yang muncul dari permukaannya mengeluarkan suara parau. Gambarnya membawaku kembali ke sana, menarikku ke dalam cerita yang belum bisa kumengerti. Ketika aku memandang kaca di seberang ruangan, bayanganku lambat laun mulai memudar. Lalu penglihatanku mencari keberadaan lelaki itu. Dia sedang duduk di ruang baca, sembari mengamati sebuah potret: diriku.***








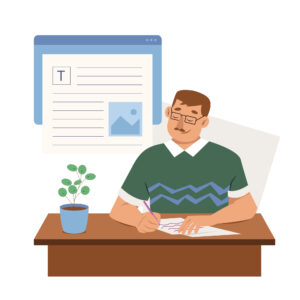

One thought on “Riuh dalam Senyap – Cerpen Karya Yuditeha”