Tes IQ telah lama dianggap sebagai alat utama untuk mengukur kecerdasan manusia. Di masyarakat modern, skor IQ sering digunakan sebagai syarat masuk sekolah, pekerjaan, bahkan menjadi tolak ukur kesuksesan intelektual dalam budaya populer. Ironisnya, di balik statusnya yang dibilang sakral, tes IQ menyimpan sejarah panjang yang kompleks dan penuh kontroversi.
Asal usulnya tidak terlepas dari obsesi ilmuwan abad ke-19 untuk mengukur segala hal, termasuk manusia. Berkaitan dengan konteks tersebut, muncul gagasan bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang bersifat tetap, dapat diwariskan secara biologis. Dan lebih berbahayanya lagi, dapat direduksi menjadi satu angka penilaian. Gagasan inilah yang menjadi permulaan bagi perkembangan tes IQ. Sekaligus, membuka pintu menuju praktik diskriminatif berbasis sains.
Sejarah tes IQ
Cikal bakal tes IQ dapat ditelusuri ke eksperimen ilmiah Sir Francis Galton, seorang tokoh eugenika yang percaya bahwa kualitas manusia, termasuk kecerdasan dan moralitas demikian bersifat hereditas. Di dalam prosesnya, Alfred Binet juga mengembangkan sistem pengukuran usia mental guna membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar.
Binet sendiri menolak anggapan bahwa kecerdasan bersifat tetap dan dapat dinilai dalam satu angka tertentu. Sayangnya, idenya disalahpahami dan diadopsi secara sempit di Amerika oleh William Stern dan Lewis Terman. Terman mengubah tes IQ menjadi alat seleksi sosial dan terang-terangan menyatakan superioritas ras tertentu atas dasar skor IQ. Hal ini mengindikasikan adanya narasi pseudo ilmiah yang semakin memperkuat rasisme struktural.
Penggunaan tes IQ secara masif dimulai pada era perang dunia 1, ketika militer AS menggunakan nilainya untuk menyortir tentara. Akibar bias bahasa dan budaya, banyak imigran mendapatkan skor rendah, bukan karena rendahnya kecerdasan, melainkan karena tidak familiar dengan konteks pengujian. Tes ini menjadi alat penempatan sosial, bukan pemetaan potensi. David Wechsler kemudian memperbaiki pendekatan ini dengan mengembangkan deviation IQ yang membandingkan individu terhadap rata-rata kelompok usia. Meskipun perbaikan ini signifikan secara statistik, tetap tidak menjawab pertanyaan mendasar bahwa sejauh mana IQ benar-benar mencerminkan kecerdasan manusia yang multidimensional.
Sejarah IQ adalah bukti bahwa pengukuran ilmiah tidak bebas nilai. Tes IQ yang awalnya dimaksudkan untuk iklusi pendidikan berubah menjadi alat eksklusi sosial. Kritik terhadap IQ bukan semata-mata penolakan terhadap pengukuran, melainkan penolakan terhadap penyederhanaan manusia menjadi sebuah angka tertentu. Sehingga, menjadi warisan sejarah yang masih memengaruhi praktik psikologi hingga hari ini.
Wacana IQ di masyarakat Indonesia
Di tengah arus deras digitalisasi wacana, media sosial Indonesia kini menjadi lahan subur bagi reproduksi narasi-narasi mengenai kecerdasan. Beredar luas klaim bahwa IQ masyarakat Indonesia setara dengan gorila, atau bahwa Indonesia menduduki peringkat terbawah dalam hal pendidikan di Asia Tenggara.
Klaim-klaim ini disampaikan secara vulgar oleh sejumlah influencer dan dikutip oleh media arus utama, bahkan dalam diskursus yang serius seperti dalam konten Raymond Chin, laporan CNN Indonesia, dan beragam diskursus lainnya. Pernyataan semacam ini tidah hanya keliru secara metodologis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana angka IQ dijadikan senjata simbolik untuk mempermalukan, alih-alih membangun kesadaran kritis.
Narasi rendah IQ yang dikemas dalam bahasa populer ini memperkuat inferiority mental kompleks di tengah masyarakat. Di satu sisi, ia membentuk citra kolektif bahwa bangsa ini bodoh secara struktural. Di sisi lain, ia membuka ruang bagi bentuk-bentuk manipulasi baru yang menjual jalan keluar dan kebodohan semu tersebut.
Akal imitasi bekerja secara halus dalam skema ini ketika masyarakat diyakinkan bahwa kecerdasan bisa dicapai melalui langkah-langkah instan, dengan asumsi bahwa IQ adalah satu-satunya penentu. Hal ini pada akhirnya menciptakan ilusi bahwa siapa pun sebenarnya bisa meningkatkan IQ-nya hanya dengan mengikuti formula tertentu yang dijual melalui kelas daring,webinar, atau produk edukasi berbayar.
Profesor Stella Christie: nilai IQ bukan angka yang statis
Kritik terhadap pendekatan ini mulai disuarakan oleh beberapa tokoh pendidikan dan psikologi. Profesor Stella Christie misalnya, dengan tegas menyatakan bahwa nilai IQ bukanlah angka yang statis. Kecerdasan manusia dapat berkembang dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, akses terhadap pendidikan, dan pengalaman belajar.
Perspektif ini kembali ditegaskan oleh para edukator seperti Ferry Irwandi dan Sabda Zenius yang menolak penyederhanaan kecerdasan ke dalam satu titik tolak numerik. Mereka menekankan pentingnya melihat potensi manusia sebagai spektrum luas. Artinya, yang tidak bisa ditangkap sepenuhnya oleh angka dalam satu lembar hasil tes.
Sayangnya, suara-suara ini masih tenggelam di tengah dominasi konten viral yang mengeksploitasi IQ rendah sebagai bahan olok-olok atau sebagai dalih untuk menjual superioritas intelektual tertentu. Maka, di sinilah bahayanya, bahwa angka IQ yang sejatinya bersifat relatif dan kontekstual malah diperlakyukan sebagai kebenaran absolut yang menentukan nilai dan harga diri seseorang. Budaya digital saat ini memproduksi ulang ilusi kecerdasan dalam bentuk performatif, bukan substantif yang berpusat pada citra dan pemahaman.
Fenomena akal imitasi semacam ini menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang mengalami krisis kecerdasan, melainkan krisis cara memahami kecerdasan itu sendiri. Ketika masyarakat diajak percaya bahwa IQ rendah adalah takdir, dan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan meniru model kepintaran yang sempit dan seragam, maka yang diciptakan bukanlah kemajuan, melainkan wacana stratifikasi sosial berbasis mitos ilmiah. Yang dipertontonkan ke publik bukanlah kecerdasan autentik, melainkan akal imitasi pola pikir yang menjadikan simbol sebagai substansi.
Kapitalisme pengetahuan dan simulakra kecerdasan
Kapitalisme pengetahuan kerap menyerupai pasar gelap yang tersusun rapi. Ia memperjualbelikan sesuatu yang sukar diukur, lalu mengemasnya dalam tanda-tanda yang mudah dikenali. Di dalam mekanisme ini, kecerdasan hadir sebagai proses yang menurut saya sebagai komoditas yang siap diedarkan. Skor IQ, sertifikat, gelar, dan jargon ilmiah ringan berfungsi sebagai barang dagangan dengan harga yang ditentukan oleh daya tarik visual dan legitimasi simbolik yang melekat padanya.
Dalam pengalaman saya membaca wacana seputar IQ, skor angka sering diperlakukan layaknya bukti absolut tentang kemampuan berpikir seseorang. Padahal, saya melihat bahwa pengukurannya menyimpan asumsi yang terbatas, bias budaya, dan konteks yang sering diabaikan.
Ketika Baudrillard berbicara tentang simulakra, saya merasa analogi terkait hal ini seakan tepat bahwa skor IQ kini sering berfungsi sebagai tanda yang terlepas dari realitas kecerdasan itu sendiri, bahkan berdiri sebagai simbol yang punya kehidupannya sendiri di mata publik.
Banyak fenomena semacam ini yang terlihat jelas di ruang digital. Sejumlah orang memamerkan skor IQ atau atribut pintar lainnya di media sosial, seakan itu adalah kunci legitimasi intelektual. Akal imitasi bekerja halus di sini dengan cara seseorang mengulang istilah psikologi atau neuroscience yang mereka dengan tanpa benar-benar memahaminya. Penonton yang haus akan tanda kecerdasan menerimanya begitu saja sebagai bukti otoritas.
Komodifikasi hasrat ingin terlihat pintar
Kapitalisme pengetahuan memanfaatkan situasi ini untuk memonetisasi hasrat kolektif agar terlihat pintar. Produk-produk yang menjanjikan peningkatan kecerdasan, kursus instan, atau konten singkat yang membungkus teori rumit menjadi mudah dicerna, laris di pasaran. Sayangnya, bentuk-bentuk ini justru mengikis kesabaran dan ketekunan yang dibutuhkan untuk memahami sesuatu secara mendalam.
Ledakan informasi di era digital bukannya memperdalam pemahaman, malah berisiko memperbanyak lapisan tanda yang menutup substansi. Masyarakat dibanjiri citra kecerdasan, sementara kesadaran kritis untuk menelusuri dan menguji makna di baliknya semakin menipis. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kita berpotensi menukar kecerdasan yang laihr dari proses reflektif dan agumentatif dengan versi imitasi yang hanya kuat di permukaan semata.
Penulis: M. Ariby Zahron
Editor: Muhammad Ridhoi







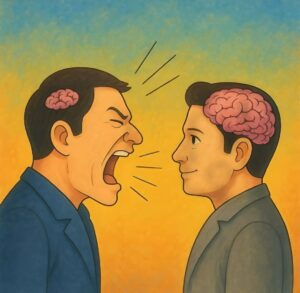

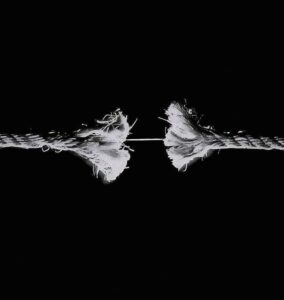

Ajiiib….