Inisiasi progresif yang digerakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup alias Pandawara telah menjadi katalisator perdebatan kontroversial dalam diskursus ekologis di jagad media sosial. Apabila teman-teman mencermati, Pantai Loji di Sukabumi, Sungai Citarum, dan Kali Krukut di Depok yang telah dibersihkan dari sampah oleh Pandawara, kerap menjadi sorotan dan memicu dialektika di antara netizen maupun para pemerhati lingkungan.
Kita mengenal adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) yang berfungsi sebagai kerangka hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, sering kali pengelolaan lingkungan hidup hanya terpusat pada pemanfaatan lingkungan sebagai objek pembangunan, padahal seharusnya mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
Pengelolaan lingkungan yang dimaksud merujuk pada upaya pengaturan dan pemeliharaan ekosistem melalui pendekatan manajerial. Pendekatan ini berlandaskan pada kapasitas manusia dalam meregulasi serta memodifikasi lingkungan demi membentuk suatu konsepsi yang secara terminologis dikenal sebagai eco-friendly.
Namun, jika merujuk pada premis awal, tampak jelas bahwa realitas yang terjadi justru berlawanan dengan prinsip keberlanjutan, mengingat masih maraknya perilaku destruktif yang dilakukan oleh masyarakat tanpa kesadaran ekologis, seperti penumpukan limbah secara sembarangan, serta lemahnya peran pemerintah yang cenderung apatis terhadap degradasi lingkungan di kawasan urban, aliran sungai, ekosistem alam, hingga wilayah pedesaan.
Oleh karena itu, diperlukan dekonstruksi paradigma pengelolaan lingkungan yang tidak hanya bersandar pada retorika eco-friendly, tetapi juga menitikberatkan pada keberlanjutan ekologis dengan pendekatan berbasis environmental justice, guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keseimbangan ekosistem.
Krisis Lingkungan dan Paradigma Transformasi Ekologis
Pernyataan ini pada hakikatnya lahir dari sikap kekecewaan kolektif terhadap masifnya deforestasi, akibat industrialisasi yang dikendalikan oleh otoritas negara, tingginya akumulasi limbah domestik maupun anorganik yang mencemari ekosistem laut dan daratan, serta volume limbah industri yang terus meningkat akibat model pembangunan yang eksploitatif. Idealnya, manusia harus memiliki kesadaran bahwa lingkungan bukan sekadar entitas yang pasif, melainkan sebuah sistem bio-kompleks yang terdiri dari elemen-elemen biotik—yang saling berinteraksi dalam sebuah siklus ekologi yang dikenal sebagai ecosystem dynamics
Di dalam tatanan ekologis ini, manusia mendapatkan komponen bioesensial untuk menopang proses produksi dan konsumsi, dengan tanah, udara, dan air berfungsi sebagai substrat fundamental bagi keberlanjutan organisme dari makro hingga mikro yang berperan sentral dalam stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Namun, di tengah kompleksitas krisis lingkungan, muncul perdebatan epistemologis: apakah perubahan harus dimulai melalui regulasi partisipatif publik atau melalui intervensi kebijakan top-down policy intervention?
Dengan kata lain, apakah solusi terhadap krisis ekologi lebih bergantung pada kesadaran individu untuk mengubah paradigma ekologis mereka, ataukah perubahan hanya akan terjadi ketika regulasi yang ketat dan kepemimpinan yang transformatif hadir sebagai mekanisme koersif untuk mengarahkan masyarakat menuju keberlanjutan?
From Post to Change: Pandawara adalah Musuh Para Pemalas
Aksi nyata dalam pelestarian lingkungan seringkali lebih berdampak ketimbang sekadar kritik di media sosial. Inisiatif berbasis komunitas yang berorientasi pada perubahan konkret tentunya menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Apabila meninjau ulang layaknya Pandawara yang saban hari kita temukan dalam berbagai aksinya, sebenarnya Pandawara bukanlah pembersih lingkungan, melainkan refleksi atas rendahnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap keberlanjutan ekosistem.
Gerakan semacam ini jelas mencerminkan bahwa kesadaran ekologis tidak hanya dapat diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi, tetapi juga melalui tindakan kolektif yang lahir dari inisiatif masyarakat. Keberadaan mereka mematahkan anggapan bahwa perubahan hanya bisa terjadi dari atas ke bawah. Justru, pergerakan yang tumbuh dari akar rumput dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun, bahwa15% di antaranya berakhir di lautan atau daerah perairan. Hal ini menegaskan bahwa masalah sampah bukan hanya tentang kebersihan, tetapi juga ancaman bagi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.
Esensi fundamental dari permasalahan ini tidak hanya terbatas pada eliminasi limbah yang tampak secara kasat mata, tetapi juga mencakup rekonstruksi paradigma ekologis yang menghindarkan masyarakat dari persepsi bahwa lingkungan hanyalah tempat pembuangan akhir. Gerakan sosial berbasis lingkungan, seperti Pandawara, telah menjadi katalisator munculnya inisiatif serupa, seperti Bumantara dan berbagai greenfluencer lainnya—yang menunjukkan bahwa intervensi nyata mampu menggerakkan kesadaran kolektif.
Namun, tanpa transformasi pola pikir yang sistematis, segala upaya ini berisiko terjebak dalam siklus repetitif tanpa dampak jangka panjang. Oleh karenanya, peran edukasi lingkungan menjadi semakin krusial—bukan sekadar menanamkan pentingnya kebersihan, melainkan juga menumbuhkan kesadaran intrinsik bahwa keberlanjutan ekosistem merupakan tanggung jawab bersama yang harus diinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan.
Pandawara: Sanitasi Sosial atau Gebrakan Revolusi Ekologi?
Jika kita menilik kembali perdebatan mendasar mengenai apakah Pandawara merepresentasikan sebuah gebrakan ekologis atau sekadar aksi sanitasi sosial semata, jawabannya sangat bergantung pada perspektif kita dalam merespons fenomena ini.
Jika mereka hanya diperlakukan sebagai entitas voluntarisme kebersihan tanpa ada refleksi kritis terhadap urgensi perubahan struktural, maka dampak jangka panjangnya akan mengalami stagnasi. Dalam hal ini, masyarakat yang berada dalam strata elit sosial atau bangsawan seakan hanya menjadi penonton pasif yang menikmati, mengamati, dan meremehkan inisiatif tersebut tanpa adanya internalisasi kesadaran ekologis yang mampu mereformasi pola pikir kolektif terhadap keberlanjutan lingkungan.
Sebaliknya, jika gerakan ini diposisikan sebagai katalis perubahan, maka Pandawara dapat berfungsi sebagai titik awal dari sebuah revolusi ekologi yang lebih masif. Dalam hal ini, sanitasi sosial yang mereka lakukan tidak hanya terbatas pada pembersihan fisik, tetapi juga merupakan strategi resistensi ekologis terhadap aktor maupun oknum destruktif yang secara eksploitatif mereduksi daya dukung ekosistem.
Dengan kata lain, gerakan ini bukan sekadar respons terhadap akumulasi limbah, tetapi sebuah bentuk perjuangan ekologis (lutte écologique) dalam menghadapi praktik-praktik yang secara sistematis mendegradasi lingkungan melalui eksploitasi sumber daya agresif dan tidak berkelanjutan.
Transformasi Sistemik dan Kesadaran Kolektif untuk Keberlanjutan
Pada akhirnya, permasalahan lingkungan tidak dapat disederhanakan sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah atau segelintir aktivis, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem sosial-ekologis yang menuntut partisipasi kolektif dalam upaya mitigasi dan adaptasi.
Tanpa adanya kesadaran ekologis yang terinternalisasi secara struktural, degradasi lingkungan akan terus berlanjut sebagai dampak dari mekanisme eksploitasi antropogenik yang mementingkan akumulasi kapital tanpa memperhitungkan daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, gerakan semacam ini harus dilihat sebagai pemantik ekologis (ecological ignition) yang menuntut reaksi berantai dalam bentuk socio-environmental transformation yang lebih sistemik.
Jika inisiatif yang telah muncul hanya diperlakukan sebagai fenomena temporer tanpa ada kesinambungan, maka dampaknya akan mengalami regresi dan kembali tereduksi menjadi sekadar upaya sporadis yang tidak berorientasi jangka panjang. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan bukan hanya sekadar aksi seremonial berbasis voluntarisme, melainkan advokasi lingkungan yang terinstitusionalisasi—yang nantinya bakal mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, hingga model kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak lagi eksploitatif.
Keberlanjutan sebuah gerakan tidak bergantung pada seberapa sering aksi dilakukan, tetapi pada seberapa jauh ia mampu menciptakan paradigma baru yang menggeser cara manusia berinteraksi dengan alam. Melihat narasi dan merenungkannya semacam ini bukan sekadar respons terhadap krisis, melainkan sebuah tuntutan atas perubahan sistemik yang harus diwujudkan sebelum ekosistem mencapai titik irreversible collapse (kehancuran yang tidak dapat dipulihkan).
Maka, untuk saat ini, pilihan ada di tangan kita, apakah membiarkan kesadaran ini tereduksi menjadi sekadar narasi, atau menjadikannya fondasi bagi revolusi ekologis yang lebih substansial.
Penulis: Muhammad Ariby Zahron
Editor: Muhammad Ridhoi





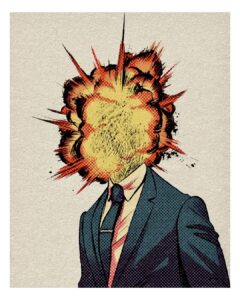




One thought on “Pandawara Sebenarnya Gebrakan Ekologis atau Sanitasi Masyarakat Belaka? ”