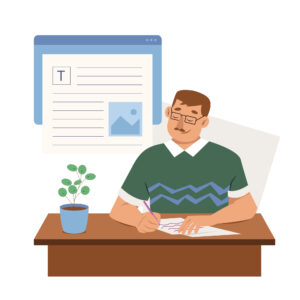Hidup itu persis skripsi yang tak pernah berhasil direvisi: dosen selalu dicemooh, printer selalu roboh, dan mahasiswa selalu merasa bodoh. Setiawan merasakannya penuh-penuh, sebab malam ini ia sedang meluncur di atas motor bebek Asrul—bukan ke kampus, bukan ke perpustakaan, tapi ke rumah misterius di lereng gunung untuk mencari ayam cemani.
“Wan, kali ini aku yakin seratus persen,” teriak Asrul di depan, helmnya longgar, semangatnya kencang.
Setiawan menahan tawa getir. Sahabatnya itu dikenal di kampus sebagai spesialis mistis. Asrul percaya bahwa nasi yang membasi adalah bentuk komunikasi roh leluhur, dan bahwa rokok yang cepat habis artinya sedang diisap jin. Bagi Setiawan, semua itu omong kosong. Namun iming-iming upah satu miliar dari acara peresmian RSUD di Bangkalan itu membungkam logikanya. Separuh untuk Asrul, separuh untuknya. 500 juta—cukup untuk menghapus beban hidupnya.
Angin malam menusuk dan menampar keras.
Membuat mereka teringat kembali perjalanan pertama ini. Waktu itu, mereka menjajal ayam cemani aduan yang katanya tak pernah kalah. Kandangnya gelap, penjaganya bersuara berat, narasinya menyeramkan. “Ayam ini sudah membunuh 7 ayam jago hanya dengan sekali seruduk,” katanya.
Asrul nyaris menitikkan air mata. “Wan, ini pasti yang kita cari!”
Setiawan hanya memandang ayam itu. Ia tampak gagah, benar, bulunya hitam pekat. Tapi pada akhirnya, apalah arti ayam? Seekor unggas yang kerjaannya berkokok, berak di teras tetangga, dan kabur kalau dikejar. Mereka menguji darahnya—sret, tetesan merah, semerah rapotnya sewaktu masih sekolah, merah pucat menetes ke tanah. Biasa. Sama sekali tidak mistis.
Asrul terpukul. “Tapi… katanya—”
“Katanya, katanya, hidup ini memang penuh katanya. Yang nyata itu kita dibodohin cok cok anjing lah!.” Setiawan hampir tertawa, sekaligus ingin menangis.
Sejak saat itu, ia ingin langsung berhenti. Namun lihatlah dirinya sekarang: masih juga di atas motor Asrul, menuju lokasi ayam kedua. Logikanya menjerit dalam kedap, tapi dompetnya berharap. Alasannya sederhana: manusia tidak pernah benar-benar mencari kebenaran, yang mereka cari cuma cara agar besok bisa makan enak.
Kembali ke motor.
“Wan,” Asrul kembali berteriak, penuh keyakinan, “ayam kedua ini seumur hidup nggak pernah nyentuh tanah!”
Setiawan mendengus. “Kalau gitu itu ayam apa drone?”
Motor bebek Asrul akhirnya berhenti di depan sebuah rumah megah di lereng gunung. Bukan rumah, lebih mirip vila. Cat putih, pagar besi, lampu taman. Setiawan langsung merasa aneh—masa ayam mistis tinggal di real estate?
“Wan, jangan mbantah dulu. Mitosnya jelas: ayam ini nggak pernah nyentuh tanah seumur hidup. Disayang banget sama pemiliknya,” kata Asrul dengan wajah yakin, seakan sedang memperkenalkan calon menantu ke orang tua.
Setiawan hanya menggeleng. Ayam yang nggak pernah nyentuh tanah? Kalau dipikir, itu lebih mirip lifestyle artis ketimbang ayam: tidur di kasur, makan bunga kehidupan, malas gerak.
Mereka masuk. Seorang pria paruh baya menyambut ramah, lalu membawa mereka ke halaman belakang. Di sana, seekor ayam hitam mengintip dari sangkar gantung, benar-benar tak pernah menginjak tanah. Pemiliknya menambahkan cerita dengan penuh kebanggaan, “Ayam ini hanya aktif malam hari. Makannya kembang tujuh rupa. Beda dengan ayam kampung biasa.”
Asrul hampir bertepuk tangan. Setiawan, meski sinis, mulai ikut berdegup—bayangan uang 500 juta menggantung di kepalanya.
“Coba kita lihat darahnya,” kata Asrul.
Pisau kecil disiapkan. Sret. Darah menetes ke mangkuk kecil. Hitam. Hitam pekat, lebih gelap daripada kopi robusta.
Setiawan menelan ludah. Ini dia. 500 juta. Ia sudah membayangkan membeli motor baru, bahkan mungkin kabur dari kota dan dosennya yang menyebalkan, atau mungkin menghajikan kedua orang tuanya demi menghapus jejak dosa-dosanya. Tangannya gemetar. Ia nyaris berdoa pada Tuhan yang selama ini ia abaikan.
Lalu hujan turun.
Bukan hujan biasa, tapi deras, brutal, seperti sengaja dipanggil oleh alam semesta untuk menertawakan mereka. Bulunya perlahan luntur. Cat hitam terbawa air, menetes di tanah. Darah berikutnya yang keluar—merah biasa.
Setiawan menatap kosong. Rasanya seperti menonton dosen tersenyum setelah bilang, “Revisimu salah semua.” Asrul masih mencoba menyangkal. “Mungkin… mungkin ayamnya lagi sakit, Wan.”
“Bukan sakit. Tolol. Kita ini lagi ditipu. Ayam ini disulap jadi gothic,” kata Setiawan, menahan tawa getir.
Mereka pulang dengan motor bebek basah kuyup. Asrul masih menyimpan secuil harapan, tapi Setiawan hanya merasa hidupnya seperti kembang tujuh rupa: wangi di awal, garing di akhir. Ia mulai bertanya-tanya: kalau ayam ini semua palsu, apakah satu miliar itu juga cuma fatamorgana?
***
Pencarian masih dilanjutkan. Motor tua Asrul meraung pelan, lebih mirip suara sapi lapar daripada kendaraan bermotor. Rantai sudah melilit seadanya dengan kawat, lampu depan meredup seperti lilin mau padam. Mereka berdua menembus jalan setapak hutan pedalaman, gelap, penuh lubang, dan aroma lembab tanah basah.
Setiawan duduk di jok belakang dengan wajah pucat. Lelah, frustasi, dan nyaris menyerah. Ia menghembuskan asap rokoknya ke udara gelap.
“Srul, aku udah nggak kuat. Tiga hari kita ngejar ayam mistis kayak orang gila. Nggak ketemu-ketemu. Kayak hidupku: lari dari satu masalah ke masalah lain, tapi ujung-ujungnya cuma kaya dikejar hutang, dosen, dan ayam fiktif,” keluh Setiawan.
Asrul menyalakan lampu sein padahal mereka jelas-jelas di tengah hutan tanpa rambu dan persimpangan. “Wan, kalau aku nyerah, aku nggak bisa nolong temanku.”
Setiawan melirik malas. “Teman? Teman yang mana lagi cok?”
Asrul menarik napas panjang, nada suaranya lebih serius dari biasanya. “Ada temenku, kuli bangunan. Orang baik. Tapi salah tangkap. Polisi kira dia maling motor. Padahal motor itu motorku. Sekarang dia di penjara. Aku janji ngasih uang buat tebus dia. Kalau nggak ada uang, dia bisa jadi tape di sel. Makanya, Wan. Aku harus cari ayam ini. Biarpun aneh, biarpun kayak mimpi pas greges, tapi ini satu-satunya harapan.”
Setiawan mendadak diam. Ada getir yang menggantung di dadanya. Ia ingin meringis kecil, ingin mencaci, tapi kata-kata Asrul terlalu jujur untuk ditertawakan. Hidup memang suka bercanda dengan cara yang jahat.
Mereka tiba di sebuah gubuk di tengah hutan. Anehnya, rumah reot itu ramai. Penuh orang-orang aneh dengan dandanan setengah dukun, setengah cosplay badut pasar malam. Ada yang pakai ikat kepala kain batik, ada yang mengenakan jubah hitam murahan, ada yang bawa botol mineral berisi air bening sambil dijual seharga knalpot motor bekas.
Seorang pria berambut gondrong dengan jenggot acak-acakan menyambut. “Pawang ayam cemani masih di dalam kamar. Lagi komunikasi sama arwah tuyul gondrong. Katanya si tuyul mau ngasih keris sakti.”
Setiawan melotot. “Tuyul gondrong? Mana ada tuyul gondrong? Tuyul tuh botak, kecil, lincah. Kalau gondrong itu namanya mahasiswa seni rupa.”
Asrul justru memasang wajah serius. “Wan, jangan remehin. Dunia ini luas. Rambut bisa tumbuh di mana aja, bahkan di kepala tuyul.”
Mereka menunggu setengah sabar. Suasana rumah makin geje. Seorang lelaki mendekati Setiawan sambil membuka tas kain. Ia menawari jimat.
“Mas, ini ada mangkok belah seribu. Khasiatnya bikin makanan nggak bakal basi. Taruh nasi setahun pun masih wangi.”
Setiawan menatap mangkok itu. Catnya sudah mengelupas, jelas buatan pabrik murahan. “Kalau beneran, kenapa kamu jual? Kenapa nggak bikin warung sendiri? Modalnya murah, menunya nasi isi ulang aja.”
Orang itu tersinggung tapi tidak menyerah. Ia mengeluarkan korek api kuning. “Kalau ini, korek sakti dari kuburan wali. Api ini bisa bikin rokok berubah rasa. Bisa mintain rasa apa aja. Kopi, STMJ, durian, sampai sate padang.”
Setiawan menahan tawa. “Kalau aku mintanya rasa aman karena nerima gaji bulanan, bisa?”
Belum selesai ia mengejek, muncul lagi tawaran lebih absurd: segumpal rambut pirang dalam plastik. “Ini rambut kuntilanak Belanda. Bisa buat pelet selebgram. Tinggal dibakar, terus sebut nama username target. Dijamin chat langsung dibales.”
Setiawan hampir meledak ngakak, tapi hanya menutup muka dengan kedua tangan. Hidup benar-benar dungu, tapi tawa yang keluar terasa getir. Karena di balik semua omong kosong ini, orang-orang sebenarnya hanya cari harapan. Sama seperti dirinya. Sama seperti Asrul.
Akhirnya pintu kamar terbuka. Muncul seorang pria kurus, berkaos gambar macan siliwangi dengan celana jarik, matanya merah karena kebanyakan asap dupa. Dialah sang pawang ayam. Semua orang menunduk penuh khidmat, seolah yang keluar itu nabi unggas.
Dengan suara bergetar ia berkata, “Ayam cemani yang kalian cari… kecil, seukuran telapak tangan. Makanannya asap dupa maharaja. Dan… dia bisa bicara. Bahasa Jawa dialek Banyumas.”
Orang-orang bersorak kagum. Asrul terpana, seperti anak kecil mendengar dongeng.
Tapi Setiawan sudah tidak kuat lagi. Ia berdiri, menginjak puntung rokok. “Sudah cukup. Aku muak. Ini semua kebohongan. Ayam bisa ngomong? Bahasa ngapak pula? Ayam aja nggak ngerti kalau dia dijadiin nasi goreng, apalagi datengin rejeki.”
Ia berjalan keluar, meninggalkan gubuk itu.
Hutan masih gelap, motor tua menunggu, rantainya berkarat. Hujan rintik mulai turun. Setiawan tahu ia belum kaya, belum sukses, dan mungkin tak akan pernah dapat ayam mistis itu. Tapi setidaknya, malam itu ia masih bisa memilih: lebih baik pulang dengan tangan kosong, daripada tinggal di rumah yang penuh dengan janji palsu.
Asrul menyusul dari belakang, wajahnya bingung. “Wan, kita pulang? Serius?”
Setiawan menatapnya, lalu tertawa. Tawanya keras, getir, seperti menertawakan hidup yang tak pernah berhenti menipu.
Setiawan menarik gas motor seolah hendak mengiris malam dengan knalpotnya sendiri. Jalan pedalaman itu gelap, penuh lubang, tapi ia tidak peduli. Amarahnya lebih besar daripada rasa takut. “Sialan! Semua mitologi itu omong kosong! Cemani, tuyul gondrong, rambut kuntilanak Belanda! Semua cuma dagelan buat orang gila!JANCOK ANJING ANJING COK COK” teriaknya sambil memaki udara. Daun-daun jati di pinggir jalan pun seakan menunduk, pura-pura tidak dengar ocehan mahasiswa frustasi ini.
Asrul di jok belakang menggenggam erat bahu temannya. “Wan, pelan dikit. Dengar aku. Hidup memang absurd, tapi absurd itu bukan berarti palsu. Kau tahu? Aku dapet mimpi semalam. Ada bisikan. Katanya, esok kau akan kaya raya. Mungkin ayam cemani itu cuma simbol. Mungkin yang kita cari bukan ayam, tapi jalan hidup.”
Kata-katanya melayang-layang seperti khutbah tanpa jamaah. Setiawan tak menjawab. Baginya, suara Asrul hanyalah dengung nyamuk di telinga. Ia bisu, ia tuli, ia menolak lagi-lagi ditipu mimpi, wangsit, dan bisikan aneh yang hanya membawa lelah. Ia hanya menatap jalan gelap dengan pandangan kosong—seolah jika ia ngebut cukup cepat, semua beban bisa tertinggal di belakang.
Lalu, sebuah sorot lampu putih muncul mendadak dari tikungan. Sebuah mobil pick-up tua, berisi keranjang ayam hidup, berjalan pelan di jalurnya sendiri. Setiawan terlambat menyadari. Teriakan singkat, benturan keras, lalu dunia pecah jadi puing-puing.
Motor itu terguling. Suara ayam-ayam berkokok panik bercampur dengan dentuman besi. Tubuh Asrul terpental, menghantam aspal, dan diam. Sang sahabat, yang barusan memegang pundaknya dengan hangat, kini terbujur tanpa nafas, dengan darah hangat menodai jalan. Setiawan terpaku.
“Kalo aja… aku nggak emosi… kalau aja aku tadi mau denger…” suaranya patah, bercampur tangis dan ludah. Malam itu, dunia terasa kejam sekaligus lawak: seorang yang hidup demi uang 500 juta palsu justru meninggal menabrak pick-up penuh ayam biasa—bukan ayam mistis, bukan ayam miliaran, hanya ayam konsumsi. Ironi yang terlalu murahan bahkan untuk sandiwara Tuhan.
**
Setahun kemudian, Setiawan sudah berubah. Tidak ada lagi motor butut tumpangan, tidak ada lagi wajah nelangsa. Kini ia duduk di rumah permanen, dengan mobil baru di garasi. Ia tidak menemukan ayam cemani asli, tapi ia menjual ratusan jimat palsu: bulu ayam dicelup tinta hitam, batu kali dijual sebagai “kerikil wali”, bahkan plastik hitam dibentuk menyerupai kuku ayam mistis. Semua laku. Semua orang percaya.
Ia tertawa getir setiap kali menghitung uang. Bukan karena ia bahagia, melainkan karena ia tahu: yang mati sia-sia bukan hanya Asrul, tapi juga hatinya sendiri. Dunia mistis tidak perlu ada; kebohongan sudah cukup untuk membuatnya kaya raya.
***
Oleh: VIPER BERBISABERBISIKBERBISIKBERSISIK