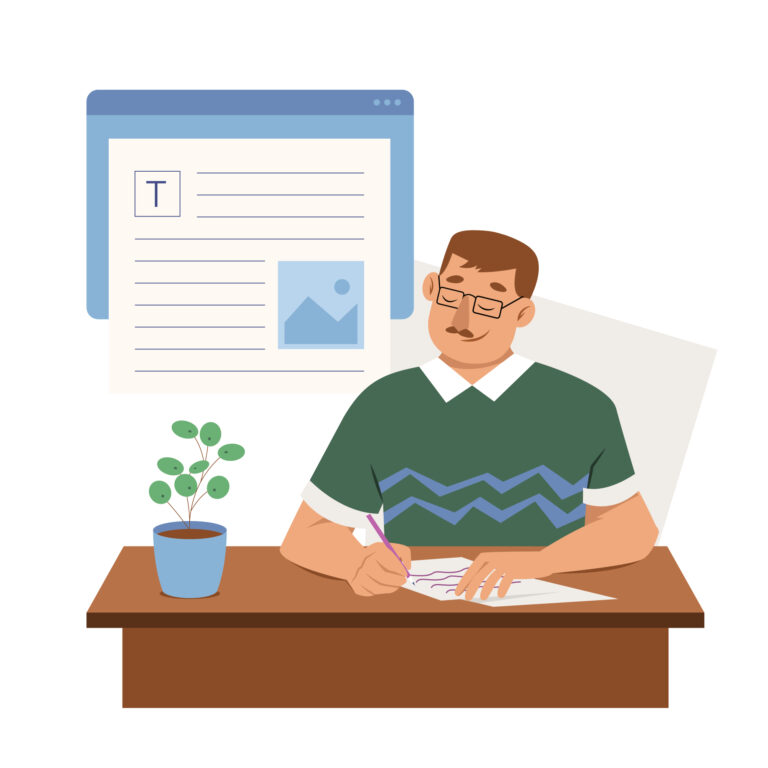Assalamualaikum. Cerpenmu sudah saya terima dan sudah saya jajaki kemungkinan pemuatannya. Saran dari saya sebagai redaktur, nama Toek ganti dengan nama yang berkarakter dan khas. Nama Toek gak bunyi. Untuk nama tidak abeh. Syekh Lincir misalnya, itu nama yang lucu. Cepat cari nama lagi untuk cerpenmu Capres Tanpa Kepala itu. Revisi lagi. Kirimkan nanti malam. Kalau ternyata cerpenmu buruk, langsung kukembalikan.
Pesan dari redaktur langsung ia kirim lewat hapeku pribadi. Ia Pak Habib mantan redaktur nasional. Pengalaman seperti ini sering terjadi pada tulisanku. Dan menururtku itu biasa dan wajar saja, tapi tidak selalu wajib diindahkan, terkadang berujung kekonyolan. Penulis dan redaktur juga punya pemikiran berbeda, dan tentu punya alasan masing-masing. Aku memilih tokoh namanya Toek, ya karena nama itu aneh. Aku suka membuat yang aneh dalam tulisanku, termasuk ketika membuat nama tokoh.
Terus aku menggunakan nama Syekh Lincir, itu karena lincir di daerahku berdekatan pengertiannya dengan licik. Kalau aku buat nama tokohnya, misalnya Syekh Abdullah atau Syekh Abdul Wahhab, menurutku itu kesannya biasa dan datar seperti yang ada dalam novel-novel islami yang sering aku temukan. Dan aku tidak mau menulis yang biasa-biasa, tapi harus luar biasa, termasuk dalam penamaan tokoh.
Kenapa aku membuat lincir itu seorang syekh, dan memliki karakter licik? Jawabannya, karena aku ingin melakukan pendobrakan dalam karya sastra yang kususun. Dan memang maksudku ingin menyentil mereka yang senang dipuji masyarakat dengan sebutan itu, sehingga mereka merasa mulia, dan melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, memandang rendah orang lain. Anehnya masyarakat yang memuji-muji itu lupa diri, ia juga punya kesucian jiwa untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Mereka yang terlalu mengagung-agungkan syekh merasa semua yang dilakukan syekh benar, sehingga tak boleh dikritisi. Mereka tidak lagi menimbang- nimbang. Jika redaktur itu tidak setuju dengan caraku seperti itu, bahkan jika ia mengatakan ceritaku tidak nyambung, itu hak dia. Dan aku juga punya hak untuk tidak mengindahkan saran-sarannya.
“Jadi abang tidak mau mengganti nama tokoh itu?” Tanya istriku yang baru saja kuajak cerita tentang kisah naskahku yang terbaru itu.
“Tidak, sayang,” aku mendekatkan tubuhku ke tubuhnya, mencium keningnya. Aku perhatikan wajahnya yang kesal, dan aku memeluknya, ia berontak melepas pelukan itu, kemudian ia pergi, dan aku mengikutinya.
“Kan cuma tinggal ganti nama saja, setelah itu akan diterbitkan. Lumayan lo bang honornya di media itu. Ganti sajalah namanya sesuai selera redaktur Bang. Apalah arti sebuah nama dalam tokoh cerita? Mengalah sajalah, biar naskahnya dimuat, dan dapat duit.” Aku sudah tahu kemana pikiran istriku sebagai mata duitan. Dan ia tidak memahami seorang pengarang karya sastra tidak sembarangan menyelibkan nama tokoh dalam ceritanya.
“Ini bukan soal mengalah atau tidak, juga bukan soal diterbitkan atau tidak. Apalagi soal honor tulisan, ” jawabku mencium pipinya yang manis. Ia yang berpakaian seksi menyerupai telanjang mundur ke belakang duduk di atas kursi biru. Kakinya yang kanan ia angkat diletak diatas kaki kiri.
* * *
Keputusan redaktur sudah bulat. Ia menolak tulisanku. Aku yang tidak mau mengganti nama sesuai saran dari redaktur membuat istriku marah. “Apasih beratnya kalau cuma mengganti nama. Tinggal hapus doang, lalu ketik nama baru, kirmkankan lagi, lalu dimuat dan dapat honor.” Aku tahu ke mana mata istriku memandang. Ia tidak mengerti penulis punya ciri khas sendiri, punya aturan sendiri dan punya ketetapan sendiri yang tidak bisa digoyahkan olehsiapapun, termasuk redaktur, apalagi honor tulisan. Bukannya penulis tidak berterimakasih pada redaktur tentang penyuntingan naskah yang tentu sulit dilakukan.
Tapi ada titik-titik tertentu yang penulis tidak mau disunting. “Dulu, begitu terbit tulisan abang, seminggu setelah itu abang selalu mengajakku ke kafe, makan enak kita di sana. Lalu abang ajak aku ke pasar, abang belikan aku baju baru. Sekarang sebanyak itu tulisan abang terbit di media, jarang-jarang sekarang abang bawa aku keluar.” Istriku hanya Ibu rumah tangga biasa. Di depan rumah kami ada sebuah warung kecil sebagai pekerjaan tamabahan untuknya. Ia lulusan SMA dan tak pernah duduk di bangku kuliah. Usianya masih 23 tahun, 14 tahun di bawahku.
Terkadang kelakuannya yang seperti anak-anak membuatku naik pitam. Ketika aku menjelaskan semuanya tak pernah masuk diakalnya. Tapi aku tak putus asa. “Rani sayang, dulu media itu hampir keseluruhan memberi honor pada penulisnya, dan itu jumlahnya lumayan. Sekarang banyak media yang tidak berhonor dengan berbagai alasan.” Begitu lembut suaraku menjelaskan. Bukan itu saja, aku coba mencium keningnya dan bibrnya agar ia bergairah dan tidak marah. Seharusnya dari dulu semasih kami berpacaran perlu aku jelaskan sama perempuan itu, aku yang berpropesi sebagai penulis lepas nasibnya tergantung dan untung-untungan. Intinya seorang penulis yang berharap kehidupannya bisa dibangun dengan karya-karyanya, itu sulit sekali terjadi di negriku, seperti mimpi. Bahkan bisa jadi itu keinginan yang tak pernah terwujud.
“Kalau begitu untuk apa menulis capek-capek, tidak diberi honor setelah dimuat. Tulisan yang tidak diberi honor berarti tulisan yang tidak dihargai.” Cepat sekali ia ngomong seperti itu. Kata-katanya sebuah opini yang lahir dari pemikirannya. Mungkin benar mungkin juga tidak. Komentar yang ia sampaikan sudah jadi pembicaraan yang masih hangat sampai sekarang di kehidupan para penulis. “Sayang, penulis itu ada penulis pemula, dan ada penulis senior,” aku mengelus-ngelus pundaknya. Ia yang tadi duduk terpaku sekarang ia bangkit berdiri.
“Bedanya apa?”
“Kalau penulis pemula, apalagi mereka yang tidak ada mentornya. Mereka butuh sekali orang untuk mengoreksi naskah-naskah yang mereka tulis itu, tanpa aku bermaksud mengatakan penulis senior tidak butuh mentor. Jika tulisan mereka lolos di salah satu media, berarti tulisan itu jelas lolos kurasi setelah diseleksi ketat, walaupun tidak berhonor. Itu yang membuat senang hati mereka, dan pelan-pelan nanti mereka bisa mengoreksi naskah sendiri. Jadi belajar menulis itu, bisa dari tulisan sendiri yang sudah diedit oleh redaktur.” Istriku menggoyang-goyangkan
tubuhnya dengan gerak kecil. Aku harap ia mengerti penjelasanku.
“Kalau penulis senior?” ucapnya tergesa-gesa.
“Ya, kemungkinan besar, walaupun tidak suatu kepastian dia bisa memilih ke mana karyanya dikirim. Ke media berhonor atau tidak.”
“Memangnya penulis pemula tidak boleh memilih media untuk pengiriman tulisannya.”
“Bukan begitu maksudku. Kalau dia penulis senior mengirim ke media yang berhonor, secara logika lebih besar kemungkinannya untuk diterbitkan, daripada penulis pemula.” Istriku tidak setuju. “Seharusnya redaktur itu netral dong, dia tidak melihat siapa penulisnya, senior atau bukan. Tapi ia fokus pada kualitas tulisan. Kalau perlu ketika mengirim tulisan tidak usah dicantumkan nama. Kalau layak muat, baru dikonfirmasi.” Tumben istriku pintar, ucapku dalam hati yang bergidik.
“Ya, begitu juga bagus. Redaktur sangat selektif memilih karya untuk diterbitkan. Dia memang tidak membedakan penulis senior atau pemula. Aku berkata seperti itu, karena mereka penulis senior tentu sudah tahu cerita seperti apa yang dibutuhkan media tertentu sesuai genre masing-masing, yang mungkin penulis pemula asal gas aja. Yang penting buat tulisan lalu kirimkan ke media mana saja. Suka-suka hati mereka. Kau mengertikan maksudku Jenong,” aku memegang hidungnya yang pesek. Semasa ia gadis, aku sering memanggilnya dengan sebutan
itu, yang mebuatnya memukul-mukul pundakku, akhirnya memelukku.
“Paham. Tapi aku tetap tidak setuju kalau tulisan yang lolos lewat seleksi yang super ketat tidak dibayar, alias tidak berhonor.” Ia tidak satu pendapat denganku.