Pada waktu-waktu yang seharusnya Sucipto merasa gembira karena tujuannya hampir tercapai, sesuatu yang aneh terjadi. Akhir-akhir ini, setiap malam dalam tidurnya, ia kedatangan dua tamu. Mereka begitu menakutkan, kadang muncul berdua, kadang sendiri-sendiri. Kedatangan mereka selalu diikuti suara tangis dan tawa yang tidak biasa, serasa meneror dan menggedor-gedor jantungnya. Setiap kali sosok itu mengunjunginya, Sucipto merasa mereka hendak menelan tubuhnya. Sebab itu, setiap mereka muncul, Sucipto cemas dan bila hal itu terus terjadi ia bisa jadi gila.
Kegelisahan Sucipto selalu terbawa dalam tidur, bahkan kata istrinya, Sucipto suka mengigau tidak jelas. Akan tetapi, setelah bangun, ia selalu lupa dengan dua sosok itu. Namun ia yakin bahwa mereka berwujud dan hidup, bahkan bercakap-cakap dengannya.
Keadaan itu mula-mula karena perilaku Sucipto yang mulai berubah, yang bukan semata-mata karena dorongan atas kesadarannya tetapi karena keinginan terselubung. Ia pikir tidak ada cara yang paling senyap dan halus untuk mencapai keinginannya, kecuali cara itu. Tentu saja Sucipto tidak ingin mendadak aneh di mata warga Desa Tugu. Maka, siasat itu, ia rencanakan masak-masak. Ketika keadaan telah larut, ia melakukannya pelan-pelan, agar warga desa tidak mengendus niatnya yang sedang mengincar sesuatu.
Dua tahun sebelum hari pemilihan kepala desa tiba, ia sudah mempersiapkan diri. Ia akan mengambil hati warga yang menghendaki pemimpin yang ramah, jujur, adil, sederhana, religius, dan dermawan itu tidak dengan kata-kata apalagi spanduk-spanduk yang bertebaran, atau baliho besar yang mempertontonkan wajahnya, melainkan dengan tindakan.
Ia yang mula-mula enggan bergaul, mulai berbaur dengan warga. Sucipto mengobral senyum, salam, dan sapa kepada siapa saja. Ia mulai ikut begadang untuk meronda, dan tidak segan masuk ke got atau mengayun cangkul pada saat ikut bekerja bakti. Semua itu dilakukan secara bertahap. Sucipto takut warga akan curiga jika perubahan dirinya terjadi tiba-tiba.
Sucipto juga mulai aktif ikut rapat-rapat di balai desa, sesekali ia menyumbang pendapat, yang terang-terangan ia tonjolkan keberpihakannya kepada petani dan nelayan, bahkan sering ngotot sampai melotot supaya dikatakan bahwa ia benar-benar peduli. Pendek kata, dirinyalah yang paling gigih. Pandangan kagum orang-orang membuatnya yakin bahwa mereka mulai percaya, dan lama kelamaan sesuai target Sucipto, penduduk desa mulai menyadarkan persoalan mereka pada pendapat-pendapatnya.
Sucipto berkeliling ke seluruh dusun, di mana Desa Tugu menjadi ibu kota kecamatannya. Ada tiga dusun, yang semuanya berbatas muara, dan masing-masing dihubungkan dengan dua jembatan kayu yang sudah tua dan bobrok. Kepada warga ia katakan, jembatan-jembatan itu sudah tidak layak, bisa mengancam nyawa. Warga boleh minta kepada pemerintah untuk membuat yang baru melalui Kepala Desa Tugu yang sedang menjabat. Ia meyakinkan mereka supaya tidak takut untuk bicara, kalau perlu mendesak karena hal itu sudah menjadi hak warga.
Rumah-rumah warga yang reyot, ia usulkan untuk dibedah. Kata Sucipto, “Satu untuk semua, semua untuk satu.” Sebenarnya hal itu bukan kata-katanya sendiri, melainkan hanya jiplakan dari apa yang pernah ia dengar di layar televisi. Ia lakukan itu supaya terlihat seperti pejuang. Dan benar, dalam benak warga desa, Sucipto dianggap sangat berjasa.
Sucipto yang mulai terhormat, mengajak semua warga bergotong-royong untuk bedah rumah. Ia tidak hanya memberikan sumbangan tenaga, tetapi juga biaya, yang sebenarnya ia maksudkan untuk memancing perhatian para pedagang, pengusaha, pegawai pemerintah yang kaya di kecamatan itu. Ia tahu tabiat mereka selalu tidak mau kalah dan senang dipuji. Usahanya menuai hasil karena telinga mereka menjadi panas lantas ikut menyumbang. Tindakan-tindakannya itu sebenarnya membuat Sucipto kelelahan, tetapi ia berpikir bahwa umpan harus besar untuk menangkap ikan yang besar.
Citra Sucipto yang dahulu sebagai laki-laki tua sinis, yang hanya memikirkan bagaimana caranya untung besar dari kios sembakonya, sembari kerja sambilan sebagai rentenir, sedikit demi sedikit buyar. Sucipto tahu, perubahan dirinya itu sering dibicarakan, yang katanya mereka syukuri.
“Saya sudah tua, hampir bau tanah, beruntung saya belum mampus. Saya ingin berguna untuk saudara-saudara sekampung saya, karena kalau saya mati, kalianlah yang mengurusi jenazah dan liang kubur saya. Masak saya mandi sendiri, pakai kafan sendiri, dan gali kubur sendiri, kan ngeri, ya, toh?!” tanggap Sucipto.
Penjelasan itu diamini banyak orang, mereka mengangguk-angguk menunjukkan sikap hormat. Terlebih setelah ia rajin ikut salat berjamaah dan memperhatikan kebutuhan masjid, seperti mengecat, mengganti balon yang lebih terang, dan membelikan speaker baru yang lebih jernih suaranya. Sucipto benar-benar dianggap telah menjadi orang yang saleh.
Selama hampir dua tahun Sucipto mencicil kebaikan, sampai waktu pemilihan hampir tiba. Dugaan Sucipto terbukti, tanpa diminta, sebagian besar warga Desa Tugu senang hati mengusung Sucipto sebagai calon kepala desa berikutnya tanpa harus ia mengajukan diri. Warga menilai Suciptolah satu-satunya yang pantas. Semua syarat-syarat sebagai pemimpin tampak pada dirinya. Tidak perlu pula ia repot-repot mengurusi ini dan itu, warga desa telah berdatangan ke rumahnya dengan antusias membantu.
Keadaan sempat memanas ketika warga bersitegang dengan pendukung kepala desa sebelumnya yang ingin menjabat lagi, yang jumlahnya kalah banyak dengan pendukung Sucipto. Ia tidak ikut nimbrung, dan berpura-pura menolak dengan mengatakan bahwa ia terlalu kecil untuk jabatan itu. Ketika ia menolak, justru warga semakin garang mendukungnya. Wibawa Sucipto menjadi lebih besar dari sebelumnya di mata mereka. “Harus Tuan Sucipto,” kata mereka, yang dahulunya nama Sucipto hanya diberi embel-embel Mas atau Om. Kata mereka lagi, “Tuan Sucipto adalah kami, dan kami adalah Tuan Sucipto!” Kalimat itu bahkan tidak diduga oleh Sucipto akan keluar dari mulut warga desa.
***
Pada sebuah malam yang esoknya Sucipto akan dilantik menjadi kepala desa baru, dua tamu itu datang lagi. Pada mimpinya, mereka tidak lagi hanya berdua, mereka bersama jembatan yang berjalan seperti raksasa, bersama rumah-rumah reyot bermulut besar, jalan yang menganga, dan kata-kata yang terbang hendak menyambar Sucipto seperti burung gagak. “Selamat Sucipto,” kata dua tamu itu sambil tertawa dan menangis.
Ketika bangun, tubuhnya berkeringat dan gemetar. Wujud kedua tamu itu akhirnya bisa diingat Sucipto. Keduanya adalah Sucipto sendiri. Yang pertama sosok berwajah dirinya, yang suka tertawa mengejek. Yang lain, juga sosok berwajah dirinya, yang suka menangis pilu, seperti tangis kehilangan orang terkasih.
Pagi hari itu, dengan pakaian necis dan rambut yang diminyaki, dengan perasaan yang tidak enak karena dibayangi oleh mimpi semalam, ketika Sucipto berdiri di atas podium untuk menyampaikan sambutan di acara pelantikannya, ia menjadi sangat terkejut. Warga yang duduk di kursi, semua berwajah dirinya. Mereka menangis dan tertawa silih berganti persis seperti yang ada dalam mimpinya. Suara-suara mereka meremangkan bulu kuduk Sucipto, seolah-olah berlomba menyusup masuk melalui setiap lubang tubuhnya, bahkan pori-pori kulitnya. Suara-suara itu menyelusup ke dalam tempurung kepala, rongga dada, dan aliran darahnya. Sucipto menutup kedua mata dan telinganya. Napasnya sesak, lantas tubuhnya ambruk dan tidak pernah bisa bangun lagi.
Warga desa berkabung. Kesedihan mendalam menyelimutinya. Tenda-tenda di depan rumah Sucipto disesaki orang-orang yang datang. Tangis kehilangan yang dibarengi ucapan puja-puji atas kebaikan Sucipto selama dua tahun terakhir terus mengalir. Kata mereka, jasa Sucipto akan mereka kenang sepanjang masa.
“Sepertinya Tuan Sucipto sudah punya firasat dia bakal meninggal, makanya dia berubah jadi orang baik,” kata seorang pelayat.
“Beruntung sekali dia,” timpal pelayat yang lain.
Di antara mereka yang datang, ada yang bergumam: “Ada bagusnya warga desa membuat patung kehormatan bagi Tuan Sucipto. Beliau sedang tersenyum dan mengepalkan satu tangan ke atas. Jika perlu patung itu untuk mengganti tugu yang letaknya tepat di jantung desa. Sepertinya, pantas sekali!”***









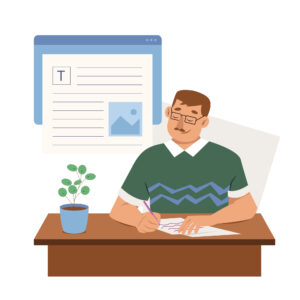

One thought on “Sucipto – Cerpen Diana Rustam”