Di negeri yang katanya menjunjung tinggi meritokrasi, kita justru menyaksikan fenomena “ngeritokrasi”—sebuah sistem di mana yang ngeri justru yang meraih posisi, sementara yang berkompeten hanya bisa gigit jari. Fenomena ini bukan lagi kabar burung. Ia nyata, terasa, dan bahkan dipertontonkan di layar kaca kita setiap hari. Dari birokrasi, BUMN, kampus, hingga dunia kerja: semua terkena imbas.
Perwira Tinggi jadi Eselon I Kementerian
Awal 2024 publik dikejutkan oleh penunjukan seorang perwira tinggi TNI sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini sontak menuai kritik keras karena yang bersangkutan belum pensiun secara resmi dari militer saat diangkat. Undang-Undang TNI Pasal 47 jelas menyatakan bahwa prajurit aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali di kementerian pertahanan dan lembaga tertentu, dan itu pun harus atas persetujuan presiden serta setelah pensiun.
Penunjukan ini menyisakan banyak pertanyaan. Apakah ini bentuk pelanggaran hukum atau strategi memperkuat pengawasan fiskal dengan militerisasi birokrasi? Yang jelas, hal ini menyuburkan kesan bahwa loyalitas lebih penting daripada integritas atau kompetensi. Di sinilah ngeritokrasi muncul sebagai wajah baru kekuasaan yang mengabaikan aturan demi kenyamanan politik.
Usulan Perpanjangan Masa Pensiun ASN
Tak lama setelah itu, muncul usulan dari Korpri agar usia pensiun ASN diperpanjang menjadi 70 tahun bagi jabatan fungsional utama. Alasannya: agar pengalaman dan keahlian bisa lebih lama dimanfaatkan. Tetapi, di tengah kondisi di mana 7 juta orang Indonesia masih menganggur, dan jutaan lulusan baru kesulitan mencari kerja, usulan ini terdengar seperti lelucon yang basi. Di mana empatinya?
Ketika anak-anak muda berebut lowongan CPNS, para senior justru ingin bertahan lebih lama di kursi empuknya. Bukannya memberi ruang, justru mempersempit kesempatan generasi baru. Akibatnya, regenerasi birokrasi yang sehat tertunda, inovasi tersendat, dan yang bertahan hanya yang pandai menyusun laporan fiktif demi TPP dan honor tambahan.
Gelombang PHK dan Janji Lapangan Kerja yang Menguap
Sementara itu, janji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja masih jadi retorika kampanye. Tahun 2025 baru berjalan setengah, tapi lebih dari 70 ribu pekerja sudah di- PHK. Bahkan menurut data Katadata, sektor startup yang digadang-gadang menjadi masa depan digital justru menyumbang PHK terbanyak. Perusahaan seperti eFishery bahkan dilaporkan memecat 98% karyawannya, menyisakan kekosongan dan kegetiran.
PHK masif ini mengingatkan kita bahwa retorika tentang lapangan kerja sering kali berseberangan dengan kenyataan. Yang dijanjikan adalah pekerjaan, yang terjadi adalah pengusiran. Yang dirancang adalah unicorn, yang muncul adalah tikus-tikus birokrasi yang menjilat demi jabatan.
Dari Relawan ke Kursi Empuk Komisaris BUMN
Kita juga menyaksikan bagaimana kursi-kursi komisaris dan direksi BUMN diisi oleh para relawan politik. Tak usah heran bila nama-nama yang muncul adalah mereka yang aktif di kampanye, punya jasa elektoral, atau sekadar teman segolongan. Tak perlu latar belakang relevan, yang penting loyal dan bisa diajak kompromi.
Kementerian BUMN pun makin mirip biro penempatan politikus pensiun. Asesmen kompetensi direksi hanya formalitas. Semua sudah dikondisikan. Pertandingan dibuka, tapi pemenangnya sudah diumumkan sejak awal. Sementara pegawai kompeten hanya bisa tepuk tangan, pura-pura ikut seleksi, lalu kembali bekerja dengan frustrasi.
Pendidikan Tinggi dan Matinya Kepakaran
Ironi lainnya terjadi di dunia akademik. Bukannya mengembangkan ilmu pengetahuan, kampus kini ramai menjadi pabrik gelar dan pengelola unit usaha. Perguruan tinggi negeri berlomba-lomba menjadi PTN BH demi otonomi penuh—yang sayangnya lebih fokus pada peningkatan pendapatan non-akademik daripada kualitas riset.
Gelar doktor dan profesor honoris causa diberikan dengan mudah. Bahkan kepada selebritas, pejabat, politisi, dan pengusaha yang kontribusinya terhadap ilmu nyaris nihil. Di sisi lain, akademisi yang benar-benar mencurahkan hidupnya pada riset, terhalang syarat administratif yang makin absurd. Untuk jadi guru besar, tak cukup magnum opus atau karya monumental—harus ada SK, angka kredit, dan dukungan politis.
Seperti kata Tom Nichols dalam The Death of Expertise, ketika suara ahli tak lagi didengar, maka kebijakan akan lahir dari kebisingan, bukan dari kebijaksanaan. Negara yang tak menghormati kepakaran adalah negara yang siap menukar masa depannya demi kepuasan hari ini.
Ngeritokrasi Masuk ke Semua Lini dan Terlalu Pintar Tidak Jadi Apa-apa
Fenomena ngeritokrasi ini merasuk ke semua lini. Di kampus, di birokrasi, di perusahaan, bahkan di komisi daerah. Saya sendiri pernah mengikuti seleksi terbuka sebuah komisioner di daerah. Saya telah siapkan visi, misi, dan program dan presentasi dengan sungguh-sungguh. Tapi saya tahu, siapa yang akan dipilih sudah dikondisikan. Salah satu anggota dewan yang terhormat bahkan berkata, “Kami menghargai kompetensi saudara, tapi mohon maklum, ini proses politik.” Proses politik? Maka buat apa asesmen? Buat apa fit and proper test kalau yang proper justru tak pernah fit dengan selera penguasa? Kalau setiap proses pemilihan hanya formalitas, lalu untuk siapa sebenarnya negara ini dibangun?
Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa “Terlalu pintar kadang tidak jadi apa-apa.” Pernyataan ini seolah menggambarkan betapa para intelektual kerap diabaikan dalam pusaran kekuasaan. Tak perlu heran kalau akhirnya banyak sarjana yang hanya jadi buruh, atau lebih memilih jadi pedagang online daripada jadi PNS.
Kepintaran yang tak bisa menjilat memang percuma dalam sistem ngeritokrasi. Cendekiawan dianggap cerewet, ilmuwan dipandang tidak realistis, dan sarjana hanya dihargai saat bisa membungkus program pemerintah dengan istilah keren.
Ǫuo Vadis Ngeritokrasi, Mau Sampai Kapan?
Ngeritokrasi bukan hanya soal rusaknya sistem seleksi. Ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap harapan generasi muda. Ia meruntuhkan kepercayaan bahwa kerja keras dan kompetensi akan membawa hasil. Dan yang lebih berbahaya, ia menciptakan normalisasi bahwa ketidakadilan adalah bagian dari sistem.
Bung Hatta pernah berkata, “Akan ada satu masa ketika kita harus melawan saudara bangsa sendiri, melawan KKN dan pemberontakan dalam negeri.” Sebuah peringatan yang dalam batasan tertentu sejalan dengan pemikiran Dwitunggal lainnya, Bung Karno—bahwa musuh terbesar sebuah bangsa tidak selalu datang dari luar, tapi justru dari dalam tubuhnya sendiri: korupsi, kolusi, nepotisme, dan pengkhianatan terhadap nilai keadilan.
Bila bangsa ini ingin benar-benar bangkit, kita harus mulai dari satu hal: memulihkan harga diri meritokrasi. Bukan hanya dengan regulasi, tapi juga dengan keberanian kolektif untuk berkata “tidak” pada koncoisme, nepotisme, dan semua bentuk pelecehan terhadap kecakapan. Maka ketika tidak, bersiaplah: mereka yang terlalu pintar memang tidak akan jadi apa-apa. Dan kita semua akan hidup dalam ngeri yang makin nyata: ngeritokrasi.. Ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap harapan generasi muda. Ia meruntuhkan kepercayaan bahwa kerja keras dan kompetensi akan membawa hasil. Dan yang lebih berbahaya, ia menciptakan normalisasi bahwa ketidakadilan adalah bagian dari sistem.
Kalau bangsa ini ingin benar-benar bangkit, kita harus mulai dari satu hal: memulihkan harga diri meritokrasi. Bukan hanya dengan regulasi, tapi juga dengan keberanian kolektif untuk berkata “tidak” pada koncoisme, nepotisme, dan semua bentuk pelecehan terhadap kecakapan. Jika tidak, bersiaplah: mereka yang terlalu pintar memang tidak akan jadi apa-apa. Dan kita semua akan hidup dalam ngeri yang makin nyata: ngeritokrasi.
Penulis: Probo Darono Yakti
Editor: Muhammad Ridhoi





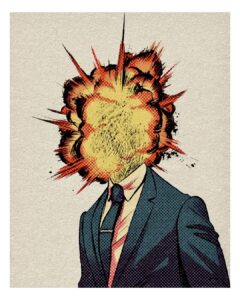



One thought on “Ngeritokrasi Merajalela, Sebab Terlalu Pintar Justru Tak Jadi Apa-Apa”