Sebagai warga kabupaten yang memutuskan untuk merantau di Ibu Kota Jawa Timur, culture shock adalah ujian pertama saya. Ujian untuk membuktikan kemampuan adaptasi seseorang. Hal ini acap kali seolah menjadi topik obrolan wajib, ketika saya menjumpai seseorang yang juga memilih untuk merantau ke Kota Surabaya.
Rabu (5/3/2025) dini hari WIB, saya singgah ke sebuah indekos seorang kawan sesama mahasiswa perantau, di Jalan Nginden Semolo, Surabaya. Kedatangan saya atas dasar memenuhi ajakan untuk nonton bareng pertandingan klub kebanggaan—Real Madrid—yang akan berlaga di perhelatan Liga Champions. Niat awal hanya ingin nobar, ternyata malah berujung jadi ajang saling sharing pengalaman sebagai sesama warga kabupaten, yang tinggal di tanah perantauan.
Seusai menonton pertandingan, saya melontarkan pertanyaan pada Markus (bukan nama sebenarnya), terkait ada-tidaknya culture shock yang pernah ia rasakan ketika pertama kali menjejakkan kaki di Surabaya. Sebagai orang yang lahir dan besar di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Markus mengakui ada banyak sekali perbedaan yang ia rasakan ketika datang ke Pulau Jawa, terutama di Kota Surabaya.
Masuk Kuliah Jalur Keberuntungan
Pria berusia 23 tahun ini pun menceritakan bagaimana akhirnya ia memutuskan untuk kuliah di Surabaya, ketimbang di NTT yang mana adalah kampung halaman sendiri. Usai tamat SMA pada tahun 2020, ia tak pernah terbesit untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mana pun. Namun, atas dasar saran dari orang tua, ia akhirnya memutuskan untuk ikut tes mandiri di Universitas Airlangga tahun 2021.
“Rata-rata anak di kampungku itu tidak ada yang tahu Unair. Aku daftar di Unair itu ya karena disuruh bapakku. Bapakku kan pernah tinggal lama di Jawa. Terus aku disuruh daftar saja di Unair. Katanya Unair itu bagus,” tutur Markus.
Dengan hanya modal nekat dan dukungan dari orang tua, ternyata ia dinyatakan lolos dan diterima di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Airlangga. “Aku awalnya bingung waktu milih jurusan karena tidak ada rencana. Terus aku lihat ada jurusan Sasindo, ya sudah aku pilih saja itu. Eh, kok lolos ternyata,” imbuh Markus sambil tertawa.
Dengan diterimanya Markus di kampus Airlangga, hal ini berarti ia harus terbang jauh meninggalkan kampung yang membesarkannya selama lebih dari dua dekade. Meski dengan berat hati, tetapi tujuannya untuk menjadi sarjana dan memenuhi harapan orang tua menguatkan dirinya. Hingga pada akhirnya Markus menjejakkan kaki untuk pertama kali di Kota Surabaya.
Niat Ingin Ramah, Sering Kali Dikira Aneh
Sebagai pendatang, Markus merasa harus selalu bersikap ramah kepada semua orang. Ia mengakui di masa awal tinggal dan menetap di Surabaya, ia selalu menyapa dan tersenyum jika berpapasan dengan bapak-bapak atau ibu-ibu di jalan. Namun, sikap ramah tamah ini justru sering kali tidak mendapat respon yang baik. Seolah Markus dianggap orang yang aneh.
“Waktu awal-awal datang dan kos di dekat kampus, aku kalau ketemu orang di jalan selalu senyum. Tapi banyak yang cuek. Semenjak itu aku kalau ketemu orang diam-diam saja. Tidak pernah senyum lagi, mungkin cuma sekedar nyapa saja,” ujar Markus dengan nada sedikit kesal.
Berangkat dari pengalaman dicuekin tersebut, pada akhirnya Markus mengerti mengapa banyak orang yang ia temui dianggapnya tidak menghargai keramah-tamahan. “Mungkin orang-orang takut kalau sama orang yang tidak kenal, kan banyak kasus kriminal, entah dibegal atau yang lainnya,” imbuhnya.
Sulit Beradaptasi dengan Sistem Perkuliahan
Markus beranggapan ternyata kuliah di Unair tak semudah yang ia bayangkan. Bahkan, di awal perkuliahan, ia sempat insecure dengan teman-teman sebaya di jurusannya. Markus merasa sistem belajar-mengajar di kelas perkuliahan sangat kontras berbeda dengan pengalamannya ketika bersekolah di kampung halamannya.
“Aku merasa minder kalau di kelas, teman-teman pintar sekali,” ucap Markus.
Mendengar ucapan Markus tersebut, lantas membuat saya kepo dengan istilah “pintar” yang dipakainya. Pintar itu yang seperti apa?
“Ya, pintar. Kayak selalu aktif di kelas, kalau dosen ada tanya-tanya itu selalu bisa jawab, dan berani tanya kalau ada pelajaran yang belum dimengerti. Kalau di sekolahku dulu tidak pernah ada yang seperti itu,” sambungnya.
Markus menjelaskan bagaimana pengalaman semasa ia sekolah dulu. Murid-murid di sekolahnya, termasuk Markus, seakan tidak pernah diberikan hak untuk berpendapat. Bahkan bertanya pun tidak berani, apalagi menyanggah pernyataan dari para guru.
“Guru itu orang yang paling ditakuti di sekolah. Sekali kau berani jawab ketika guru omong, habis kau kena pukul pasti. Karena kalau ada yang berpendapat itu dianggapnya tidak sopan,” imbuh Markus.
Melihat sistem belajar-mengajar di dunia perkuliahan yang demikian, Markus merasa kesulitan untuk beradaptasi. Pada akhirnya, jika ada dosen yang terkenal sering bertanya, atau hanya ada sedikit mahasiswa yang masuk kelas, ia lebih memilih untuk menghindar dengan membolos. Daripada harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari para dosen. Hal inilah yang membuatnya sering mengulang mata kuliah, dikarenakan presensi yang kerap lewat dari jatah maksimal.
Kerja Kelompok Seperti Kerja Sendiri
Bentuk culture shock lain yang Markus rasakan adalah semisal ketika dosen memberikan tugas kelompok di suatu mata kuliah. Menurutnya, kerja kelompok semasa di perkuliahan itu sama saja seperti tugas individu, tapi bedanya dikumpulkan jadi satu. Bahkan tak jarang ada mahasiswa yang hanya “numpang nama”, tanpa memberikan kontribusi apa-apa dalam tugas kelompok.
“Yang bikin aku heran itu kalau ada kerja kelompok, kita langsung bagi tugas begitu saja, jarang ada diskusi kelompok,” ungkap Markus.
“Kalau kita di timur itu dulu tidak seperti itu. Kalau semisal ada tugas kelompok, kita benar-benar mengerjakan sama-sama di satu tempat. Jadi, disana kita saling adu pendapat buat cari kesepakatan. Baru kalau semua anggota kelompok sepakat, kita tulis,” imbuhnya dengan penuh keheranan.
Penulis: Alvindest Martial
Editor: Muhammad Ridhoi



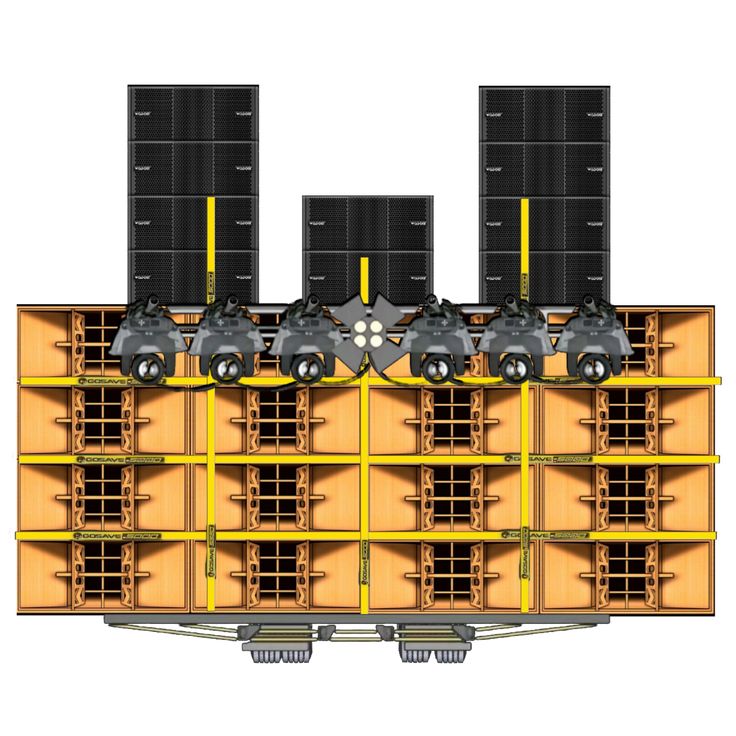




Leave a Reply