Berlangganan aplikasi dan konten digital menjadi satu dari sekian banyak riuh ramai era digital. mulai dari platform OTT (video on demand), gim, layanan musik, hingga aplikasi produktivitas. Semuanya sudah begitu akrab dengan pengeluaran masyarakat. Menurut laporan dari We Are Social, 67% warganet Indonesia (usia 16+) secara konsisten membayar layanan konten digital setiap bulan. Sebagai contoh, total pengeluaran konten digital nasional sepanjang 2024 mencapai angka US$2,64 miliar (sekitar Rp43,3 triliun) yang tumbuh sebanyak 10,9%. Angka yang cukup fantastis.
Sementara itu, seringkali kita alpa untuk menyadari kalau langganan yang tidak dipakai bukan berarti tidak membayar. Ini bukan lagi soal boros ata menghambur-hamburkan harta, melainkan soal etika kontraktual dalam era digital. Banyak perusahaan yang menyembunyikan tombol pembatalan, menunda proses berhenti langganan, atau memperbarui kontrak secara otomatis tanpa pengingat. Sebut saja saat berlangganan netflix, youtube premium, spotify, hingga iCloud.
Kekaburan Kontrak dan Kesadaran Finansial
Di dalam dunia keuangan konvensioanl, kontrak merupakan dokumen yang mengikat. Ia harus benar-benar dibaca dan ditandatangani dalam kondisi paling sadar. Namun, hari-hari ini, istilah kontrak cukup diwakili oleh tombol “agree and continue” yang ditekan tanpa pikir panjang. Ironisnya, inilah awal dari krisis personal, ketika kontrak kehilangan sifat deliberatifnya. Dokumen itu berubah menjadi mekanisme pengikat otomatis yang manipulatif agar dianggap sebagai personal yang masih sadar akan self-development, meskipun hanya demi pencitraan semata.
Fenomena ini yang kemudian disebut oleh para peneliti sebagai dark patterns, yaitu strategi desain digital yang sengaja dirancang untuk membuat pengguna sulit membatalkan layanan, atau secara tidak sadar menyetujui pengeluaran tambahan. Di dalam catatan Freedom on the Net 2024 oleh Freedom House, Indonesia termasuk negara yang rawan terpapar dark pattern karena rendahnya literasi digital kontraktual dan minimnya regulasi perlindungan konsumen digital secara tegas.
Apalagi diperparah dengan adanya sistem langganan berbasis perpanjangan otomatis (auto-renewal). Begitu pengguna memasukkan data kartu debit atau saldo e-wallet, arus uang tidak lagi dikontrol secara sadar, tetapi ditarik sistematis oleh kontrak yang tak terlihat demikian.
Tetep Bayar Sekalipun Tak Digunakan
Berlangganan aplikasi atau konten digital tak melulu karena kebutuhan. Ada gaya hidup yang hinggap disana. Memiliki akun Netflix, Youtube Premium, Spotify, hingga Apple One telah menjadi simbol konektivitas dan kenyamanan. Tanpa disadari para pengguna bukan lagi sebagai pengendali, melainkan sudah dikendalikan oleh platform.
Mirisnya, terkadang platform yang sudah berlangganan akan tetap bayar sekalipun tak digunakan. Dalam banyak kasus tidak mudah untuk menghentikan. Meminjam data dari Reddit Indonesia menunjukkan bahwa banyak pengguna yang tetap dikenakan biaya langganan bahkan setelah aplikasi tidak lagi dipakai. Salah satu pengguna menyebut bahwa mereka baru menyadari telah membayar lebih dari Rp1,5 juta dalam setahun untuk aplikasi yang tidak aktif, hanya karena lupa membatalkan.
Hal ini menunjukkan adanya kebocoran keuangan struktural, bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena sistem digital tidak didesain untuk transparansi. Audit finansial pribadi tidak memiliki instrumen otomatis yang dapat menyaring mana pengeluaran aktif dan mana pengeluaran pasif, kecuali pengguna mencatat dan meverifikasinya secara manual. Tentu, ini adalah perbuatan yang amat jarang dilakukan.
Anda Punya Platform Anda Berkuasa Penuh
Fenomena krisis kontrak digital ini mengindikasikan adanya ketimpangan kuasa antara pengguna dan penyedia layanan. Di dalam ekosistem platform digital, posisi pengguna cenderung pasif. Mereka akan tunduk patuh pada ketentuan sepihak (terms and conditions). Terlebih ketentuan itu ditulis amat panjang, kompleks, dan penuh isilah-istilah hukum yang tidak ramah bagi orang awam. Sementara itu, korporasi digital memiliki kendali penuh atas arsitektur pilihan, termasuk bagaimana opsi berlangganan, pembatalan, hingga pemrosesan data pengguna dikemas dan disembunyikan. Praktik ini pada akhirnya menciptakan power asymmetry, hilangnya otonomi pengguna dalam proses pengambilan keputusan finansial. Ketimpangan ini diperparah oleh absennya regulasi yang tegas dan responsif terhadap dinamika kontrak digital.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, misalnya, belum mengatur secara eksplisit mekanisme transparansi kontrak digital, apalagi hak atas pengingat perpanjangan untuk transaksi yang berulang. Di dalam kondisi ini, konsumsi digital telah menjadi infrastruktur ekonomi baru atau kebiasaan baru. Maka, krisis ini layak dibaca sebagai persoalan etik politik, bahwa siapa yang punya kendali atas dompet digital masyarakat, dan sejauh mana sistem memberi ruang bagi kesadaran, pembatalan, dan kedaulatan finansial individu?
Benar-benar membutuhkan atau karena tak ingin ketinggalan?
Saya sendiri baru sadar ada langganan cloud storage yang sudah enam bulan tidak saya pakai, tapi tetap dipotong otomatis. Alasan sederhana saya adalah supaya file tetap aman dan dalam hati memang membutuhkan. Namun, nyatanya tak satu pun fail itu pernah saya buka ulang. Total, hampir Rp180.000 hilang sia-sia yang kalau dikalkulasikan setara tiga kali makan enak dan satu buku baru yang benar-benar saya butuhkan.
Sebagian orang mungkin bilang “ah, cuma belasan ribu”. Tapi kalau ada lima langganan yang katanya “cuma” segitu adalah setara dengan biaya listrik sebulan. Masalahnya bukan hanya di jumlah maupun nominal yang diingat, tetapi di rasa pasrah. Kita tahu uangnya hilang, tapi merasa itu harga yang wajar untuk menjadi bagian dari ekosistem digital.
Padahal, kalau mau jujur ke diri sendiri, banyak langganan itu sekadar penanda sosial supaya bisa bilang “Saya langganan koran,” walau dibaca seminggu sekali. Atau langganan bootcamp maupun kursus daring, padahal baru buka modul pertama. Kita bayar bukan untuk manfaat, tetapi untuk ilusi bahwa seolah-olah masih produktif, masih waras, dan masih berkembang.
Tombol “setuju dan lanjutkan” bukan lagi soal persetujuan, tetapi kebiasaan yang tak sempat ditinjau. Uang mengalir, langganan jalan terus, dan kita hanya berharap saldo cukup sampai akhir bulan. Problem kontrak digital bukan hanya pada desain sistem yang licik, melainkan pada ketidaksiapan kita membacanya. Generasi yang katanya paling melek digital justru yang paling sering menjadi korban auto-renew tanpa mengingat bahwa pernah menyetujui apa. Walhasil, ini merupakan momentum untuk merebut ulang kendali atas dompet, waktu, dan perhatian. Sebab dalam dunia yang dibangun di atas ilusi produktivitas, keputusan paling radikal mungkin adalah berkata: cukup.
Penulis : Ariby Zahron
Editor : Imam Gazi Al





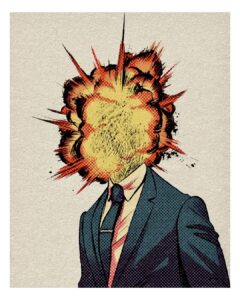




One thought on “Krisis Kontrak Berkepanjangan: Perusahaan Semaunya atau Memang Kita yang Malas Baca”