Hari Rabu di SDN Sukamurni 3 terasa seperti hari yang tak ingin dijemput siapa pun. Matahari datang dengan malas, seperti penjaga kantin yang tahu anak-anak sudah kehabisan uang jajan sejak Selasa. Di ruang kelas 3C, kipas angin tua berputar lamban, berdecit seperti suara anak kecil yang lupa caranya tertawa.
Kelas itu berisi 31 anak. Tapi ada satu anak yang duduk agak ke pojok, tak pernah benar-benar dihitung. Namanya Rega. Rambutnya seperti sapu ijuk yang habis dicuci, bajunya selalu lebih kumal dari yang lain, dan bau tubuhnya—ah, seperti bau tanah yang tak pernah terkena matahari.
Di bawah meja Rega, selalu ada kantong plastik kecil berisi sesuatu yang tak pernah dibuka. Anak-anak pernah iseng menendangnya, berharap menemukan bangkai tikus atau sisa bekal basi. Tapi saat kantong itu pecah karena diinjak, yang keluar hanya kertas-kertas lipat penuh gambar aneh dan satu dua batu kecil.
“Ia menyimpan batu kayak orang nyimpen rahasia,” kata Rio, suatu kali. Sejak itu, setiap kali Rega berjalan dengan saku penuh, anak-anak menoleh dengan curiga. Mereka takut ia sedang membawa semacam kutukan.
Di kelas, Rega lebih mirip perabot lama. Tidak pernah rusak, tapi juga tidak pernah dipakai. Ia pernah satu kelompok dengan anak-anak lain saat pelajaran IPA, tapi sejak jawabannya soal siklus air dianggap terlalu mengada-ada, setelah itu ia jarang lagi dipanggil. Anak-anak lebih suka kerja kelompok dengan kursi kosong daripada dengan Rega.
Guru mereka, Bu Erna, perempuan yang selalu memulai hari dengan mengeluh soal gaji dan mengakhiri hari dengan mengeluh soal murid. Ia suka menyebut dirinya pengabdi negara, tapi lebih mirip panitia konsumsi, yang selalu sibuk memesan nasi kotak untuk rapat, bukan sibuk mendengarkan anak-anak yang tak punya bekal.
Hari itu, hari Rabu yang gerah dan penuh aroma obat nyamuk, Bu Erna datang dengan senyum lebar. Ia membawa daftar. Katanya, akan diumumkan sepuluh anak paling unggul. Kata unggul, diucapkan seperti kata dalam undian berhadiah. Murid-murid bersemangat seperti mau lomba makan kerupuk. Beberapa bahkan merapikan rambut, seolah nilai matematika bisa berubah karena belahan rambut yang tepat.
Rega tidak berharap apa pun. Ia malah sibuk mencoret kertas dengan pensil tumpul. Gambarnya tidak jelas, mungkin seekor burung atau sepatu. Tak ada yang peduli.
Ketika nama-nama diumumkan, sorak-sorai meledak. Siska berseru keras sekali, padahal ia hanya peringkat enam. Rio menyenggol pundak Farel, berkata, “Kita dapet nasi kotak, Bro!” Nasi kotak, ternyata motivasi yang lebih hebat daripada nilai.
Bu Erna membuka kotak pertama. Isinya nasi, telur balado, sambal yang terlalu merah, dan kerupuk yang sudah lemas. Ia menunjukkannya ke seluruh kelas seperti memperlihatkan piala juara. Anak-anak yang namanya disebut diminta maju. Mereka makan di depan kelas sambil sesekali difoto dengan ponsel guru. “Untuk dokumentasi,” katanya, meski tak ada yang tahu siapa yang akan mendokumentasikannya.
Rega diam saja. Aku tidak lapar, katanya dalam hati. Tapi itu bohong. Ia hanya tahu, menelan ludah lebih murah daripada menunjukkan wajah yang ingin ikut makan.
Dalam mimpinya semalam, Rega naik becak terbang bersama seekor kucing buta dan melewati atap sekolah yang tampak seperti kardus bekas. Ia tidak tahu arti mimpi itu, tapi ia terbangun dengan senyum. Itu cukup. Mimpi yang tidak diuji dengan soal pilihan ganda adalah satu-satunya tempat ia bisa jadi juara.
Di luar jendela, pohon mangga berdiri tenang. Dari dahan paling rendahnya, ada seutas tali rafia yang tergantung. Pernah digunakan untuk bermain tarik tambang, kini lapuk bersama kenangan.
Saat makan siang hampir selesai, seorang anak bernama Dito bertanya. Suaranya pelan tapi cukup menusuk keheningan.
“Bu, kenapa nilai enam itu gagal? Bukannya itu masih lebih dari setengah?”
Kelas hening.
Bu Erna memandang Dito seperti baru sadar anak itu masih ada di kelas. Ia tidak menjawab langsung, hanya membuka daftar nilai dan menandai sesuatu. Tangannya bergerak seperti kasir menghitung kembalian yang tidak pas.
“Karena aturan,” jawabnya. “Kalau tidak mau gagal, ya dapatkan lebih dari itu.”
“Tapi siapa yang buat aturannya, Bu?” tanya Dito, seperti anak kecil yang baru sadar dunia dibangun oleh orang-orang yang tidak hadir di kelas. Bu Erna hanya tersenyum kaku, seperti sedang mencoba menjelaskan sistem pajak kepada seekor kelinci.
Dito mengangguk, walau matanya seperti ingin bertanya lebih jauh. Tapi pelajaran sudah selesai. Dan seperti biasa, tidak ada waktu untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan pilihan ganda.
Jam dinding berdetak lambat, seolah kehabisan alasan untuk terus bergerak. Anak-anak satu per satu keluar kelas. Mereka meninggalkan bekas bungkus nasi kotak, remah kerupuk, dan bau sambal. Ruang kelas seperti tempat resepsi yang gagal.
Rega masih duduk di bangkunya. Ia menggambar lagi, kali ini lebih serius. Seekor burung. Atau mungkin bukan. Tapi ia tahu persis, makhluk di kertas itu sedang terbang. Satu-satunya orang yang menghampirinya adalah Pak Rahmat, penjaga sekolah. Pria tua dengan tubuh kecil dan topi yang selalu miring.
“Belum pulang, Ga?” Rega mengangkat bahu.
Pak Rahmat melihat kertasnya. “Burung?”
“Bukan” jawab Rega pelan. “Ini, saya.”
Pak Rahmat tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk, lalu pergi menyapu halaman.
Hari mulai sore. Di ujung lapangan, anak-anak dari kelas lain bermain bola, tertawa keras. Seseorang memanggil nama Rega, tapi ia tidak menjawab.
Esoknya, berita kecil beredar. Rega tidak masuk sekolah. Katanya sakit. Tapi minggu berlalu, lalu bulan. Rega tidak pernah kembali. Tak ada upacara perpisahan. Tidak juga pengumuman resmi. Hanya kursi di pojok yang tetap kosong.
Satu dua anak mulai menyebar cerita. Ada yang bilang Rega pindah sekolah karena menang lomba gambar tingkat kecamatan. Ada pula yang bilang ia sekarang ikut pamannya di pasar, membantu menambal sepatu sambil menjual gantungan kunci dari tutup botol. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu. Di SDN Sukamurni 3, misteri lebih mudah diterima ketimbang mengakui bahwa sesuatu bisa menghilang begitu saja.
Lalu, suatu hari di bulan Desember, SDN Sukamurni 3 menerima paket besar. Tanpa pengirim. Di dalamnya ada tumpukan lukisan di atas kertas buram. Semuanya bergambar makhluk aneh. Ada yang seperti burung dengan kaki manusia, ada yang seperti anak kecil dengan sayap lebar. Semuanya sedang terbang.
Beberapa bulan kemudian, seorang guru magang yang tidak tahu apa-apa tentang Rega menemukan sesuatu di laci paling bawah meja guru: sebuah map lusuh berisi gambar-gambar ganjil di atas kertas bergaris. Semua bergambar anak-anak, tapi wajah mereka ditutup kotak hitam seperti di berita kriminal. Di pojok masing-masing gambar, tertulis angka: 6, 6, 6, 6… begitu seterusnya.
Halaman terakhir tak bergambar. Hanya ada tulisan dengan huruf miring tak stabil, seolah ditulis sambil gemetar: Saya tidak ingin menang. Saya cuma ingin dihitung.
Tak ada yang tahu siapa yang menulis. Map itu akhirnya disimpan di lemari perpustakaan, antara buku IPA kelas 2 dan diktat Pramuka yang tak pernah dipinjam. Tidak ada yang mengaku pernah melihat Rega lagi. Tapi, sejak itu, bangku di pojok tak pernah lagi kosong, selalu saja ada anak baru yang mengapa selalu memilih duduk di sana, diam-diam, seperti sudah tahu tempatnya.***








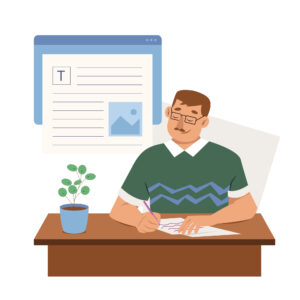

One thought on “Absen – Cerpen Karya Yuditeha”