Setiap perayaan rupanya seringkali coba dimeriahkan. Misalnya saat merayakan Hari Buku Nasional, kita sibuk bikin selebrasi perayaan. Dari membaca bersama, giveaway buku, hingga lainnya yang aku tidak tahu. Peristiwa bersama bacaan memang layak berharga dan berkesan. Sebagian orang tumbuh bersama bacaan favoritnya, sebagian lagi merasa tidak sendiri di hidup yang sepi ini sebab bacaan. Kita berterima kasih kepada penulis, penerbit, hingga orang (masyarakat) dalam kebudayaan pencipta aksara. Dengannya kita saling terhubung dengan “isi pikiran” satu sama lain. Perkenalan dengan bacaan lazimnya terjadi sejak masa kanak-kanak. Pendidikan yang
baik mengantarkan anak pada cerita hingga sebuah dunia dalam teks. Tidak sedikit pula yang baru berkenalan dengan bacaan saat sudah dewasa dan jelas ini bukanlah sebuah masalah.
Imajinasi yang Tertuduh dan Kita yang Terlalu Serius
Belakangan, Film animasi bertajuk Jumbo (2025) membuat banyak orang marah-marah. Film yang branding-nya “untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita” menjadi geger karena satu adegan: hantu keluar dari radio. Film yang jelas-jelas peruntukannya lebih bagi anak-anak tetap saja ada segelintir orang yang tidak
menerima bahwa di dunia ini ada namanya “imajinasi” dan dunia alternatif. Orang-orang dewasa kelewat serius dalam menjalani hidup. Ketika ada karya yang menawarkan sebuah dunia, mereka tidak bisa menerima apa adanya. Apalagi revolusi? Apalagi tatanan dunia yang disebut-sebut utopis padahal mungkin itu? Kita terlalu jauh dari
dunia yang kita dambakan sebab enggan beranjak. Orang sudah menganggap gila duluan atas dunia yang ditawarkan itu. Kita bisa mengira, orang-orang demikian hidupnya jauh dari imajinasi, berkhayal, dan melamun. Pikirannya selalu penuh, tapi tidak punya waktu untuk membuangnya, meredamnya dalam kegiatan bengong beberapa menit. Saking ruwetnya, orang-orang ini mencoba “membatasi” isi kepala orang lain, termasuk kepala anak-anak.
Mereka khawatir anak-anak akan tercemari imajinasi yang khayali dan tidak masuk akal. Dikiranya, hal demikian dapat merusak cara berpikir logis anak. Aku—dan mungkin kita—justru khawatir dengan orang-orang tersebut yang hidupnya sibuk khawatir. Melamunlah, bebaskanlah pikiran sendiri dari dendam-dendam dan prasangka tidak
perlu. Jika tidak bisa menciptakan dunia yang lebih baik bagi manusia, ciptakanlah dunia untuk diri sendiri. Setidaknya.
Merumahkan Rasa kedalam Kata-Kata
Aku bisa paham dan sepakat, kebebasan itu hal yang mahal. Orang pun bisa bebas berpendapat dan saling mengeluarkan kekhawatiran. Itu sebentuk cinta pula. Namun, bisakah kita satu sama lain saling mencintai sekaligus membebaskan? Tapi ternyata cinta memang sering kali datang kepada kita serupa “bangkai seekor burung” sebab “barangkali cinta tak lagi sanggup hidup di tempat lain”. M. Aan Mansyur, atau hurufkecil, menyajikan perumpamaan itu dalam puisi berjudul “buku” , “bahasa pohon-pohon tumbang” (2025)—aku tidak menulis dalam huruf kapital di awal kata sesuai aturan sebab ia “hurufkecil”.
setiap hari dunia meletakkan cinta
di tangan kita sebagai bangkai seekor burung
barangkali tepat merumahkannya ke dalam kata
barangkali cinta tak sanggup lagi
hidup di tempat lain
/
buku jatuh
dari rak. anak-
anak memungut
kata-kata
&melepaskan
mereka ke udara b e b a s
Cinta hadir sebagai bangkai seekor burung, simbol kebebasan yang mati. Mungkin? Ketika kemudian kita tafsirkan, segala bentuk ketidakbebasan, segala kekecewaan dan sakit-perihnya menghadapi dunia, hari ini manusia tuangkan ke dalam kata—“merumahkannya ke dalam kata”. Mungkin kita ingat bagaimana saran seorang psikolog/terapis/psikiater agar kita sering-sering menuliskan apa yang kita rasakan, menguraikannya pelan-pelan, hingga reda dan lega. Cinta yang tersisa itu ada dalam kata; dalam teks, dalam dunia yang pada akhirnya berada di
buku. Orang dewasa, atau siapa saja, menuangkan perasaan dan sisa-sisa cinta ke dalam tulisan, dalam buku. Juga segala gagasan yang usang tidak dibiarkan hangus dibakar kemarahan, maka dituangkan dalam kata.
Tapi bahasa, kata, buku, tidak selalu berlaku pembebasan. Orang masih bisa membelenggu pikiran dan kebebasan orang lain melaluinya. Kita masih ingat bagaimana penerbitan dan peredaran buku anak diawasi sebegitu ketat. Anak-anak dilarang bertemu bacaan yang mengandung unsur kekerasan, imajinasi liar, hingga bahasa tak santun. Itulah kerja orang-orang dewasa.
Setidaknya Untuk Melanjutkan Hidup
Kebebasan dan potensi anak dibatasi demi mimpi orang dewasa menciptakan dunia yang steril dari keburukan dan kejahatan. Padahal, pengarang dunia sekelas Steinbeck melalui East of Eden berulang kali mengatakan bahwa yang menjadikan seseorang itu manusia, ya, karena ia berbuat jahat atau terarah ke sana. Manusia tidak bisa selamanya baik dan menghindari keburukan.
Orang yang tidak sanggup menanggung risiko bersinggungan dengan kejahatan—baik sebagai citra maupun persona—dalam novel tebal dua jilid itu justru digambarkan memilih mengakhiri hidup. Untuk bertahan, dalam banyak kisah survival, manusia bertindak “jahat”. Ini mungkin lazim, meskipun kita tidak terbiasa dan berusaha menyangkalnya dengan seruan kebajikan sepanjang hayat.
Padahal, manusia tidak perlu menjadi pahlawan suci untuk hidup di dunia yang bangsat ini. Menjadi manusia artinya memiliki potensi: sewaktu-waktu berbuat baik, lain waktu tidak. Dan tidak apa-apa. Sebab kelebihan lain menjadi manusia, yakni punya kesempatan untuk berbenah dan “memperbaiki diri”. Mungkin itulah mengapa dalam agama ada konsep “taubat”. Sesederhana karena kita manusia—dan bagi yang percaya, Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun.
Ya, kita tidak perlu menjadi pahlawan suci, meskipun untuk mempertahankan optimisme, tokoh-tokoh pahlawan sering kali tercipta di dunia yang ditawarkan industri atau cerita kuno. Ketokohan dan penokohan dipelihara sebab ada pesimisme hidup sebagai manusia. Untuk dapat bertahan, orang perlu menumbuhkan harapan. Sayangnya, harapan itu kerap hadir dalam bentuk penyelamat, alih-alih mempersiapkan diri. Tapi tidak apa. Mungkin itu salah satu upaya menyelamatkan hidup—paling minimal hidup sendiri. Sebab kata banyak orang, setitik harapan sudah lebih dari cukup sebagai alasan melanjutkan hidup.
Imajinasi yang Membebaskan
Di balik keputusasaan akan kebebasan yang entah sekarang bertempat di mana, anak- anak merawat kebebasan dengan daya imajinasinya, dengan keluguannya akan dunia. Kita lihat saja bagaimana Aan Mansyur menggambarkan anak-anak dan buku.
Kepada buku yang terjatuh dari rak, entah karena peristiwa apa, anak-anak menghadapi kata-kata di dalamnya dengan membebaskan segala belenggu yang mewujud kata/bahasa atau rupa-rupa cinta lain yang ada di dalam kata itu ke udara bebas. Penyair semacam berharap cinta bisa lebih bebas dan menjangkau lebih banyak makhluk, seisi alam semesta.
Bagaimana kata-kata itu dilepaskan? Mulai dari bagaimana anak-anak tidak mematuhi tata bahasa dalam buku, sesukanya menafsirkan teks. Mulai dari kebebasan untuk berimajinasi dari teks yang ada di hadapannya. Hingga menciptakan dunia rekaan, tempat dirinya bisa membayangkan hidup di dalamnya. Lebih jauh, anak-anak akan tumbuh menjadi berani. Sungguh sebuah keberanian untuk bisa menuju “ingin”; lebih dari sekadar bermimpi/bercita-cita. Termasuk menginginkan dunia yang lebih baik, dunia yang sangat mungkin itu, tanpa menjadi orang dewasa yang menyebalkan.
Penulis : Umu Hana Amini
Editor : Muhammad Ridhoi

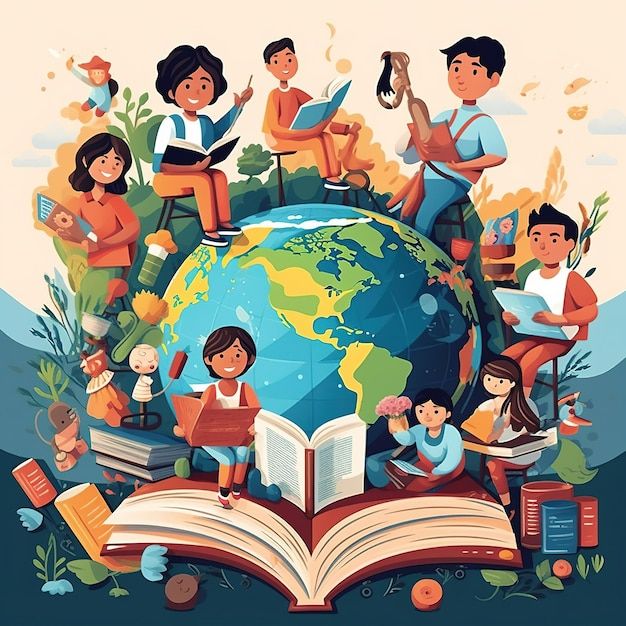



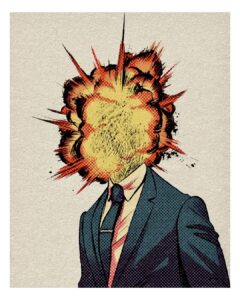




One thought on “Buku Tanpa Anak-Anak, Anak-Anak Tanpa Buku”